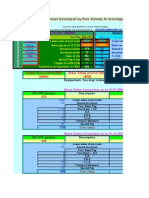Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Asnawi Ali
Transféré par
milietofathaDescription originale:
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Asnawi Ali
Transféré par
milietofathaDroits d'auteur :
Formats disponibles
HALAMAN 22
BUNGONG JAROE �KONTRAS�NO. 331�TAHUN VIII�27 APRIL - 3 MEI 2006
Asnawi Ali
Dari Jualan Kontras ke Pengasingan Skandinavia
Terobsesi untuk mengubah nasib menjadi lebih baik, Asnawi Ali, (28) memilih hijrah dari Aceh. Awalnya mantan loper koran ini menuju Malaysia, lalu mendapat suaka politik di Norwegia. Dari negara di Semenanjung Skandinavia itu, mantan pemandu (guide) wartawan mancanegara itu hijrah lagi ke Swedia dan menikah dengan wanita Aceh di sana. Besar di masa konflik berkecamuk di Aceh, Asnawi merekam dengan jeli perjalanan konflik bersenjata di Aceh, sejak Aceh Merdeka dideklarasikan Tgk Hasan Tiro. Saat ini, Asnawi yang mahir bahasa Norwegia, sedang mempersiapkan novel tentang kisah perjalanan konflik Aceh berbahasa Inggris. Perusahaan pencetaknya dia harapkan dari Amerika Serikat. Saya sengaja membidik pangsa pasar Amerika, karena alur cerita novel tersebut berkenaan dengan kisah dan peranan fiktif Amerika di Aceh, tulis Asnawi dalam surel (surat elektronik) yang dia kirimkan ke Redaksi Kontras, Senin lalu. Atas permintaan Said Kamaruzzaman dari Kontras, Asnawi menukilkan pengalamannya sejak meninggalkan dan kembali lagi ke Aceh setelah tsunami, peristiwa yang merenggut nyawa ayah dan ibunya di Banda Aceh. Asnawi juga mengisahkan sisi lain kehidupan komunitas Aceh di Swedia yang tidak melulu terkonsentrasi pada perjuangan politik memerdekakan Aceh. Ternyata, tak jauh dari pusat Kota Stockholm, terdapat meunasah Aceh untuk menampung aktivitas sosial dan keagamaan sekitar 100-an warga Aceh di sana. Berikut penuturan Asnawi untuk publik yang ia cintai di Aceh.
AYA dilahirkan di kampung kecil Meunasah Beureuleung, Grong-Grong, Pidie, tahun 1978, persis dua tahun Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Tgk Hasan Tiro dan huru-hara peperangan pun terjadi. Saya dibesarkan dalam suasana perkampungan yang nyaris tak bersinggungan dengan fasilitas modern. Tak ada listrik di rumah kami kala itu, kecuali lampu teplok. Namun, jiwa untuk merantau sudah tertanam pada jiwa saya sejak dini, sebagaimana masyarakat Pidie umumnya yang gemar merantau. Masih dalam usia kecil, saya diboyong ayah dan ibu pindah ke Banda Aceh. Ayah ingin berwirausaha di ibu kota Provinsi Aceh tersebut. Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, saya tuntaskan di Banda Aceh. Lalu, kembali lagi ke Pidie untuk masuk SMA sekaligus nyantri di Pesantren Darussadah, Teupin Raya selama tiga tahun. Setelah itu, saya kembali lagi ke Banda Aceh, kuliah di Universitas Syiah Kuala. Ketika krisis moneter melanda Nusantara pada medio 1997 yang disusul dengan lengsernya Soeharto dari tahta kekuasaanya pada bulan Mei 1998, Aceh yang masih bergolak oleh konflik, semakin terbuka bagi dunia luar. Pada saat itu saya sering ikut demo dengan teman-teman mahasiswa, terutangar kabar bahwa saya menjadi target TNI untuk ditangkap. Sejak saat itu hidup tak lagi saya rasa aman, sehingga saya hijrah ke Malaysia. Akibatnya, saya terpaksa nonaktif kuliah tahun 2000. Menjelang pergi itulah untuk terakhir kali saya lihat wajah kedua orang tua saya yang kemudian meninggal saat tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004. Ketika hijrah dari Aceh, Pulau Pinang di Malaysia, adalah tanah Melayu pertama yang saya injak, lalu pindah ke Kuala Lumpur. Dua tahun lamanya saya bemukim di ibu kota Malaysia tersebut. Karena sudah terbiasa hidup mandiri, terlunta-lunta di Malaysia pun tak menjadi ganjalan. Saya tetap gigih menyambung hidup, sampai akhirnya sebuah keluarga Melayu di Malaysia bersimpati pada saya. Tempat tinggal sementara diberikan kepada saya, juga difasilitasi untuk bekerja. Keluarga Melayu tersebut sudah akrab dengan Aceh, karena sebelumnya pun juga mereka kerap membaca konflik Aceh melalui media di Malaysia. Saya pun menganggap keluarga makcik tersebut sebagai ibu angkat. Saat di Kuala Lumpur saya berusaha berasimilasi dengan komunitas Melayu, menggunakan logat dialek mereka yang irama bahasanya terdengar agak jenaka, tapi lama-kelamaan mudah juga mengikutinya. Memohon suaka Medio April 2002 saya menerima telepon dari warga Aceh yang tinggal di Texas, USA. Dia sarankan agar saya segera memohon suaka ke Kantor UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi) Kuala Lumpur. Alasannya, pihak polis (polisi) dan imigresen (imigrasi) Malaysia sering merazia pendatang dari tanah seberang, terutama dari Aceh. Selain alasan itu, bila saya mengantongi kartu keterangan dari UNHCR, minimal saya bisa tinggal sementara di Malaysia. Kala itu tak ada tempat bagi pendatang dari tanah seberang. Polis dan imigresen Malaysia sering merazia warga yang disyaki sebagai pendatang haram (illegal immigrant) dari Indonesia. Bagi yang tanpa dokumen lengkap, apalagi diketahui berasal dari Aceh, bermacam tuduhan dialamatkan, bahkan terkesan dilebih-lebihkan. Meskipun sudah mengantongi kartu akuan terbitan dari UNHCR, aparat Malaysia sering mencari-cari alasan lain untuk menjustifikasi penangkapan warga asal Aceh. Saya yakin, pengaruh krisis ekonomi dan kebijakan politik di negara tersebut yang membuat situasi jadi sedemikian, karena saya melihat Kuala Lumpur dan Jakarta sejak dulu bagaikan adik abang. Setelah mengurus administrasi, diwawancarai staf UNHCR, dan menunggu proses hampir setahun, akhirnya diputuskan saya lulus dan ditetapkan sebagai refugee Aceh. Kemudian, pada Maret 2003 dapat kabar bahwa saya beserta rombongan refugee asal Aceh lainnya akan dibuang ke Kota Stavanger, Norwegia. Belum pernah terpikir sebelumnya dan sangat asing di telinga saya salah satu negara Skandinavia tersebut. Namun, sebagai penerima suaka politik, saya tak boleh memilih ke negara mana akan diasingkan. Beda halnya jika saya punya sanak keluarga di sebuah negara tertentu, maka lebih mudah meminta untuk ditempatkan di sana. Tapi saya tak punya siapa-siapa di luar negeri. Tiba di Skandinavia Maret 2003 saya tiba di kota minyak Stavanger, Norwegia, yang kebetulan sedang musim semi. Kala itu suhu sekitar 10 derajat Celcius. Rombongan refugee Aceh yang baru turun dari pesawat menggigil kedinginan. Meskipun jaket telah membalut tubuh, namun dengan suhu demikian sejuk --itu pertama kali saya rasakan-- membuat hampir semua refugee Aceh yang baru tiba terserang flu. Kesan pertama benar-benar asing. Bule yang berpostur tinggi untuk ukuran Asia tampak di mana-mana, ditambah bahasa Norwegia yang tidak kami pahami sepatah kata pun. Membuat semuanya serbaasing. Meskipun orang Norwegia mayoritas memahami bahasa Inggris, tapi mereka tak akan menjawab dengan bahasa Inggris jika diajak bicara, kecuali kita perkenalkan diri sebagai turis. Sungguh, bahasa Norwegia itu asing sekali di telinga saya. Belum pernah saya dengar sekalipun. Namun, grammar bahasa Norwe dengan Inggris ada sedikit kesamaan. Setiap pendatang diwajibkan mempelajari bahasa Norwe. Pendidikannya gratis, di lembaga institut bahasa Norwe. Sejak awal ketibaan, semua kebutuhan hidup kami diberikan gratis, berasal dari tunjangan sosial dalam tempo terbatas hingga para refugee mendapatkan sebuah pekerjaan. Salju yang sebelumnya hanya saya lihat di televisi, kini justru ada di depan halaman rumah tempat saya tinggal. Pernah gelas minuman yang malam harinya lupa dibawa masuk ke dalam rumah, esok paginya sisa air di dalam gelas tersebut sudah membeku jadi es. Hidup sendirian tanpa sanak keluarga, ditambah iklim seperti di dalam kulkas, membuat penyakit rindu saya pada kampung halaman kambuh (home sick). Obatnya, tak lain adalah menelepon ke Aceh, juga membaca berita tentang Aceh setiap hari melalui internet. Selain itu, saya biasanya memutar lagulagu dan film-film kocak tradisional Aceh seperti Apa Lahu, Apa Gense, Apa Lambak, dan Mae Pong yang dikirim saudara di Aceh. Lagu Aceh ternyata mudah didapat di internet secara gratis. Ini sangat menghibur saya.
Asnawi Ali
ma menuntut dicabutnya status Daerah Operasi Militer (DOM) dan adili para penjahat HAM. Pada tahun 1998 saya berkenalan dengan sejumlah wartawan dari berbagai negara. Mereka sering memakai jasa saya sebagai guide untuk peliputan berita di Pidie, daerah yang oleh GAM diklaim sebagai komando pusat. Menjadi guide seperti itu amat menyenangkan hati saya. Pertama, bisa berkenalan dengan banyak wartawan asing, kedua honorarium yang saya peroleh cukup untuk uang jajan kuliah saya. Selain menjadi guide wartawan, saya juga menjajakan Tabloid Kontras di kios koran kaki lima di Kampung Baru, Banda Aceh. Awal maraknya kasus Aceh Setelah status DOM dicabut pada 7 Agustus 1998, seiring dengan itu dinamika politik Aceh semakin memanas. Rakyat semakin sadar untuk bangkit atas nama nasionalisme Acehnya. Tugas saya sebagai guide bagi wartawan asing pun beralih membawa wartawan mancanegara ke luarmasuk Pidie untuk meliput aktivitas GAM. Beritanya disebarkan sebagai bagian dari kampanye Aceh Merdeka di luar negeri. Akibat seringnya menjadi kurir wartawan asing yang ingin meliput kasus Aceh, hingga pada suatu hari terde-
KONTRAS�NO. 331�TAHUN VIII�27 APRIL - 3 MEI 2006��
BUNGONG JAROE
HALAMAN 23
Saat melangsungkan pernikahan di Swedia.
Musim panas Agustus 2004 saya menikah dengan wanita Aceh di Swedia. Acara intat linto-nya sangat jauh. Rombongan mengendarai mobil melintasi perbatasan negara antara Norwegia dan Swedia. Proses melamarnya sejak awal, hingga proses pernikahan merujuk pada adat Aceh. Rempah makanan untuk kenduri, kami beli dari warung Asia. Tamu undangan yang datang berasal dari warga Aceh yang bermukim di Denmark, Norwegia, dan Swedia. Ada kemudahan tersendiri bagi penduduk yang bermukim di tiga negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia) tersebut bahwa bisa ke luarmasuk ketiga negara tersebut tanpa paspor. Setiap orang ke luar-masuk sesuka hatinya kapan saja tanpa ada pemeriksaan. Jika pun ada pemeriksaan, kita cukup memperlihatkan KTP saja yang berasal dari salah satu negara di Semenanjung Skandinavia tersebut. Karena jarak antara tiga negara seperti segitiga dibatasi daratan --kecuali Denmark-- jika mengendarai mobil dari Norwegia menuju Swedia pada perbatasan negara hanya ditabalkan papan batas yang tertera Velkommen till Sverige (Selamat datang di Swedia) yang menunjukkan bagi pengendara mobil bahwa dia telah sampai di perbatasan Norwegia-Swedia. Persamaan antara tiga negara tersebuat adalah mengenai bahasa. Jika ke-
tiga orang yang berasal dari negara tersebut berjumpa akan berbicara menurut bahasa masing-masing dan mereka sama-sama paham. Perbedaan hanya pada beberapa kosakata, dialek, dan intonasi. Kemudahan lainnya jika mengunjungi negara sesama Eropa adalah tidak diperlukan visa. Pernah suatu kali, medio Desember 2004 (sebelum tsunami) saya berkunjung ke Belanda ikut seminar tentang Aceh dan Papua. Saya bebas masuk hanya dengan memperlihatkan paspor suaka terbitan Norwegia. Pada pemeriksaan imigrasi di Bandara Schipol, Belanda, petugas imigrasi tidak menanyakan visa, melainkan hanya memeriksa keaslian paspor tersebut melalui scanner (pemindai) komputer. Ini karena antara sesama negara Eropa bisa berkunjung selama 60 hari tanpa memerlukan visa. Pulang pascatsunami Banyak jalan menuju Roma, begitu juga banyak jalan menuju Aceh. Ketika tusnami terjadi pada 26 Desember 2004 saya gundah dan merasa seperti durhaka jika tidak dapat menjenguk keluarga di Aceh. Selain berperang melawan Belanda, musibah tsunami ini adalah peristiwa terbanyak merenggut nyawa yang pernah terjadi dalam sejarah Aceh. Di saat orang lain belum berani pulang dengan status sebagai penerima suaka, saya sendiri persis setahun lalu memberanikan diri pulang ke Aceh. Saya menyamar dengan dalih ingin mengunjungi Nias dan Aceh untuk riset tentang tsunami. Adalah Imigrasi Norwegia yang memberikan passport non-asylum dan bantuan tiket gratis dari IOM Cabang Oslo untuk memfasilitasi keluarga korban tsunami yang ingin berziarah ke Aceh atau Sri Lanka yang juga dihantam tsunami. Fasilitas gratis tersebut langsung saja saya manfaatkan. Perjalanan pesawat sambung-menyambung dari Stavanger-Oslo-WinaSingapura-Medan, semuanya lebih dari 12 jam. Seluruh tubuh letih rasanya. Namun, dengan perasaan percaya
diri dan sedikit berlagak bak turis, saya masuki gerbang kedatangan di Bandara Polonia, Medan. Uniknya, hanya saya seorang diri yang berbaris bersama turis-turis bule di pintu kedatangan luar negeri. Menjelang hendak dipanggil petugas imigrasi, saya bertingkah seperti bule yang selalu berbicara pakai bahasa Inggris dengan para turis bule yang seakan-akan kami sudah kenal akrab. Padahal, baru pertama itu kami berjumpa. Ketika tiba giliran saya dipanggil, saya perlihatkan Alien Passport Norwegia. Dengan santai pula saya menjawab bahwa saya telah lama tinggal di Norwegia dan ke Nias serta Aceh untuk riset tentang tsunami. Karena Norwegia termasuk salah satu daftar negara Eropa penerima visa kedatangan VoA (Visa on Arrival), saya hanya membayar 25 US dolar sebagai visa turis selama sebulan, 1-30 April 2005. Semalam di Medan kemudian esok harinya saya menyambung perjalanan ke Banda Aceh. Sengaja saya pilih naik pesawat, tidak melalui jalan darat, agar tidak di-sweeping seperti dulunya ketika kita naik bus. Setiba di Banda Aceh saya sangat terkejut, karena di sana-sini bangunan hancur berantakan. Tak jauh beda dengan dampak yang diakibatkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Rumah orang tua saya di Banda Aceh, tempat saya dibesarkan sejak usia TK, hanya berbekas tangga di bagian belakang. Bagian atasnya hancur berkeping-keping dan bagian bawah hanya tinggal tapak bekas luas rumah. Ayah dan ibu saya, meninggal dalam bencana alam yang mahadahsyat tersebut. Begitu juga adik saya yang saat itu sedang membuat skripsi. Rumah dan bekas toko hanya tersisa dalam bentuk tanah sebagai warisan keluarga. Sebulan di Banda Aceh serasa tak cukup untuk menyusuri seluruh kota yang porak-poranda dan berjumpa dengan sanak keluarga yang selamat.
Meunasah Aceh Stockholm
ALAU kita mendengar nama Swedia dan menghubungkannya dengan Aceh, pastilah asumsi yang terbayang di benak pembaca suasana kancah politik Aceh, mengingat Tgk Hasan Tiro Cs memilih bermukim di Norsborg, Swedia, dan mengendalikan GAM dari sana. Akan tetapi, dalam Rubrik Bungong Jaroe kali ini saya justru ingin memaparkan hal yang sebaliknya. Sebagaimana biasanya hidup jauh dari kampung halaman, sebuah masyarakat perantau akan membentuk sebuah paguyuban sosial. Begitu juga kami orang-orang Aceh yang bermukim di Swedia. Di sini terdapat sebuah meunasah Aceh yang berada tidak jauh dari pusat Kota Stockholm. Berdiri sejak tahun 1998 dengan nama Svensk Atjehnisika Frening (SAF) --Persatuan Orang Aceh-Swedia-- kini beranggotakan lebihkurang 100 orang, termasuk kaum Hawa dan anak-anak kecil yang meliputi kota Stockholm, Hllefors, dan sekitarnya. Seperti halnya meunasah Aceh di kampung yang berfungsi sebagai aktivitas sosial dan keagamaan, meunasah Aceh di Stockholm ini juga merupakan wadah silaturahmi antarsesama perantau, tempat beribadah, berkumpul sekaligus bermusyawarah, termasuk memasak untuk kenduri keluarga, belajar pendidikan untuk semua golongan, dan tempat berolahraga. Khusus untuk olahraga, meunasah ini dapat menampung sebuah meja tenis di ruang tamu, karena arsitektur meunasah berbentuk sebuah rumah sederhana. Pemain tenis meja biasanya bermain di dalam meunasah, karena di luar tak mungkin main, mengingat cuaca yang sangat dingin. Selain mencetak kader generasi baru Aceh, hal yang paling
dititikberatkan di dalam meunasah ini adalah pendidikan agama untuk anak-anak yang lahir dan dibesarkan di negara yang non-Islam dan sekuler seperti Swedia. Kewajiban moral orang tua untuk pendidikan agama dan bahasa Aceh kepada anakanaknya adalah yang paling ditekankan supaya mereka tidak hilang identitasnya sebagai orang Aceh, kendati lahir dan dibesarkan di luar negeri. Hampir seharian penuh pada setiap hari Sabtu diadakan pengajian Alquran dan pendidikan bahasa Aceh kepada anakanak. Di hari lain, meunasah tersebut digunakan kaum Hawa serta orang tua untuk belajar bahasa Swedia dan Inggris. Di antara kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di meunasah Aceh ini adalah sembahyang tarawih, salat Idul Fitri dan Idul Adha, memperingati maulid Nabi Muhammad, dan kenduri-kenduri adat seperti yang sering dilakukan di Aceh. Aneka kegiatan yang bersifat religius atau tradisional ini kami anggap penting sekali. Terutama bagi anak Aceh yang lahir dan dibesarkan di Swedia. Cara ini akan memperkenalkan mereka terhadap identitasnya sebagai orang Islam dan anak Aceh. Orang-orang dewasa menggunakan meunasah ini untuk rapat-rapat intern yang berkenaan dengan situasi di Aceh, juga untuk menerima tamu-tamu lokal dan luar yang ingin mendapatkan first hand info dari native tentang keadaan di Nanggro Aceh. Para wanita pun memanfaatkan meunasah ini untuk aneka kegiatan khas wanita, seperti masak-memasak dan jahit-menjahit yang sering dilakukan pada hari libur, Sabtu dan Minggu. (Asnawi Ali)
Kembali ke Skandinavia Setelah sebulan di Banda Aceh, saya kembali ke Norwegia untuk berkemas merencanakan pindah bersama istri yang saat itu tinggal di Swedia. Juni 2005, merupakan bulan terakhir saya tinggal di Kota Stavanger, lalu pindah ke Swedia. Sebelumnya saya tinggal dua tahun di salah satu negara terkaya Eropa tersebut. Di Swedia yang berpenduduk 9 juta jiwa itu tak ada kesulitan dalam berkomunikasi, karena saya sudah menguasai bahasa Norwe, sehingga dalam empat bulan saja saya telah mengantongi ijazah sertifikat SFI (Svenska Fr Invadrare), semacam TOEFL-nya bahasa Swedia. Daratan Eropa yang jika diukur dari timur ke barat sama luasnya seperti dari Sabang-Merauke, setiap negara mempunyai bahasa masing-masing. Khusus bagi imigran yang ingin tinggal harus mempelajari bahasa tersebut untuk berintergrasi dan berkerja, tidak cukup dan sangat sulit bila hanya mengandalkan bahasa Inggris saja. Soal makanan, alhamdulillah, sampai saat ini tak ada masalah. Di samping banyaknya kedai Asia (warga Arab) yang menjual makanan halal, banyak juga makanan Eropa yang halal untuk dikonsumsi. Sejak tinggal di Swedia --di negara dekat dengan kutub utara ini-- setiap hari saya memantau perkembangan yang terjadi di Aceh. Internet adalah solusinya. Apalagi ada sarana chating online Yahoo Messenger dan Skype yang di dalamnya termasuk kemudahan telepon gratis antarbenua. Letak Swedia tidak lebih dari 1.000 kilmeter lagi dengan ujung kutub utara dunia. Jika memasuki musim dingin, otomatis waktu malamnya lebih lama daripada siang hari. Begitu juga sebaliknya. Kawan-kawan muslim perantauan lainnya mengatakan amat beruntung jika bulan Ramadan jatuh pada musim dingin dan agak kesulitan jika jatuh pada musim panas. Integrasi dengan warga setempat biasanya tak banyak terhadang masalah serius, meskipun pada 2001 terjadi insiden 11 Sepetember di New York. Tiga adikuasa dunia --Amerika, United Kingdom, dan Uni Eropa-- berbeda-beda menginterpretasikan tentang Islam dan di waktu bersamaan pula komunitas Islam di negara tersebut kerap memberi penjelasan tentang Islam yang sesungguhnya kepada pejabat pemerintahan di masing-masing negara. Untuk saat ini, selain menuntut ilmu sambil bekerja, saya sedang berkonsentrasi mempersiapkan sebuah novel tentang kisah perjalanan konflik Aceh dalam bahasa Inggris yang kebetulan manuskrip naskah aslinya telah selesai. Saya sedang mencari perusahaan pencetak buku di Amerika. Pertimbangan saya membidik pangsa pasar Amerika, karena alur cerita novel tersebut berkenaan dengan kisah dan peranan fiktif Amerika di Aceh. Terakhir, saya teringat pada firman Allah dalam Surah Ar Rad ayat 11, Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sampai kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Kepada rakyat Aceh tetaplah berjuang untuk mendapatkan hak hakikinya yang sejati, sehingga dapat mengubah dan menentukan nasib sendiri ke depan yang lebih adil, bermartabat, dan berdemokrasi. I
Vous aimerez peut-être aussi
- Menulis Untuk Mengubah NasibDocument5 pagesMenulis Untuk Mengubah Nasibgilang fazlurrahamanPas encore d'évaluation
- Teks Cerita SejarahDocument2 pagesTeks Cerita SejarahSupriyantoPas encore d'évaluation
- Artikel KartiniDocument12 pagesArtikel KartiniArief nugrahaPas encore d'évaluation
- BindoDocument9 pagesBindoaisyhrma ameliaPas encore d'évaluation
- 15 Pahlawan Nasional Wanita Di IndonesiaDocument15 pages15 Pahlawan Nasional Wanita Di IndonesiaPanther GunsPas encore d'évaluation
- Tentang Nyai MoeinahDocument4 pagesTentang Nyai MoeinahMerry Elvina SimanjuntakPas encore d'évaluation
- Tradisi Kematian Suku AsmatDocument10 pagesTradisi Kematian Suku AsmatAyu RistantiPas encore d'évaluation
- Biografi W.R SupratmanDocument5 pagesBiografi W.R Supratmanstepen stepanusPas encore d'évaluation
- Otobiografi Ringkas Mochtar NaimDocument9 pagesOtobiografi Ringkas Mochtar NaimIlham Rangkayo SatiPas encore d'évaluation
- Snouck HurgronjeDocument6 pagesSnouck HurgronjebeMuslimPas encore d'évaluation
- Christian Snouck HurgronjeDocument6 pagesChristian Snouck HurgronjeNifta HandayaniPas encore d'évaluation
- Bab IvDocument111 pagesBab IvAdiAriandiPas encore d'évaluation
- 15 Pahlawan Nasional Wanita Di IndonesiaDocument14 pages15 Pahlawan Nasional Wanita Di IndonesiaIndri CahyaniPas encore d'évaluation
- LAPAR - Knut HamsunDocument152 pagesLAPAR - Knut Hamsunlamhot100% (1)
- Biografi Ki Hajar DewantaraDocument7 pagesBiografi Ki Hajar DewantaraMuhammad Ramdhan Qodri0% (1)
- Kritikan Api KL Belum Terpadam Karya Faisal TehraniDocument13 pagesKritikan Api KL Belum Terpadam Karya Faisal TehraniAnonymous dV7I54K100% (2)
- Kaum Cina Di IndonesiaDocument51 pagesKaum Cina Di IndonesiadjunatrioslPas encore d'évaluation
- BiografiDocument8 pagesBiografiDwi Puspa NingrumPas encore d'évaluation
- Sejarah KartiniDocument5 pagesSejarah Kartinigizi tamansariPas encore d'évaluation
- MartirDocument3 pagesMartirBANGUNPas encore d'évaluation
- Biografi Ra KarktiniDocument7 pagesBiografi Ra KarktiniAnonymous 0hmqmCaPas encore d'évaluation
- RADEN AJENG KARTINI WPS OfficeDocument9 pagesRADEN AJENG KARTINI WPS Officesalwa putriPas encore d'évaluation
- Bangsaku MerdekaDocument2 pagesBangsaku MerdekaEvhy SalsabilahPas encore d'évaluation
- Biografi PahlawanDocument81 pagesBiografi Pahlawanhery rahmanPas encore d'évaluation
- Perjuangan Muda PDFDocument206 pagesPerjuangan Muda PDFMaikel pekei Maikel pekei100% (1)
- 12 Wanita Pahlawan Nasional IndonesiaDocument13 pages12 Wanita Pahlawan Nasional IndonesiaUNTUNGPas encore d'évaluation
- Kartini Dan Emansipasi PerempuanDocument18 pagesKartini Dan Emansipasi PerempuanAkhwat MujahidahPas encore d'évaluation
- Ainun Najmah A. (2) XII MIPA 3 Teks Cerita Sejarah SendiriDocument12 pagesAinun Najmah A. (2) XII MIPA 3 Teks Cerita Sejarah SendiriAinun NajmahPas encore d'évaluation
- Sejarah Kota Langsa PDF FreeDocument3 pagesSejarah Kota Langsa PDF FreeNoval andikaPas encore d'évaluation
- Cerpen RestukanthiDocument8 pagesCerpen Restukanthiyektiandarbeni1984Pas encore d'évaluation
- Profil Ki Hadjar DewantaraDocument30 pagesProfil Ki Hadjar DewantaraMaz TarnoPas encore d'évaluation
- Sitor Dan Aceh (Teuku Kemal Fasya, SATU HARAPAN 1501)Document4 pagesSitor Dan Aceh (Teuku Kemal Fasya, SATU HARAPAN 1501)embaulli1969Pas encore d'évaluation
- Anna Van HootenDocument15 pagesAnna Van Hootenwilliam bylandtPas encore d'évaluation
- Tugas Biografi Basa Sunda - Moch Azhar S - Xi Ips 1Document3 pagesTugas Biografi Basa Sunda - Moch Azhar S - Xi Ips 1Azhar shiddiqPas encore d'évaluation
- LatihanDocument6 pagesLatihanleoriclius7Pas encore d'évaluation
- Bab IiiDocument27 pagesBab IiiMSH YBPas encore d'évaluation
- Sejarah PonorogoDocument4 pagesSejarah PonorogosarifinPas encore d'évaluation
- Profil RA KartiniDocument11 pagesProfil RA KartiniEdwin Hastawi AtmajaPas encore d'évaluation
- Lampion Imlek Dan Keluarga SayaDocument4 pagesLampion Imlek Dan Keluarga SayaAndo OeBill TampubolonPas encore d'évaluation
- Biografi R.A KartiniDocument10 pagesBiografi R.A KartiniAyer Indarto100% (2)
- NH DiniDocument5 pagesNH DiniNovita RahmahPas encore d'évaluation
- Artikel Nh. Dini - Ensiklopedia Sastra IndonesiaDocument1 pageArtikel Nh. Dini - Ensiklopedia Sastra IndonesiaKayla Nasywa KamilaPas encore d'évaluation
- Analisis Dan Pemahaman Teks BiografiDocument8 pagesAnalisis Dan Pemahaman Teks Biografimiftahul ulumiPas encore d'évaluation
- Makala Bahasa Indonesia 30 Biografi PahlDocument67 pagesMakala Bahasa Indonesia 30 Biografi PahlIkhiPas encore d'évaluation
- Raden Ajeng KartiniDocument11 pagesRaden Ajeng KartiniAyer IndartoPas encore d'évaluation
- Biografi SastrawanDocument16 pagesBiografi SastrawanNurkasim MuhammadPas encore d'évaluation
- Wolter MonginsidiDocument5 pagesWolter MonginsidiTri Dimas HartoPas encore d'évaluation
- Tugas B.indoDocument26 pagesTugas B.indoEva HaryaniPas encore d'évaluation
- B. Sunda Kh. DewantaraDocument1 pageB. Sunda Kh. DewantarasuhendarPas encore d'évaluation
- Tun Sir Henry HDocument7 pagesTun Sir Henry HViola Voon Li WeiPas encore d'évaluation
- Gatau 2408Document4 pagesGatau 2408Agnes Monica MurislaPas encore d'évaluation
- Skripsi AdiDocument42 pagesSkripsi Adikambing mbek12100% (1)
- AcehPungo OkDocument156 pagesAcehPungo OkDedi Muzlahinur100% (3)
- Dua Jam Bersama Hasan TiroDocument4 pagesDua Jam Bersama Hasan Tiroarbi_bianglalaPas encore d'évaluation
- Biografi Cut Nyak DienDocument18 pagesBiografi Cut Nyak DienRudi FitriantoPas encore d'évaluation
- Biografi PahlawanDocument10 pagesBiografi PahlawanyunatriazPas encore d'évaluation
- So SkaDocument227 pagesSo SkaJim Randal LasuaPas encore d'évaluation
- Kelainan Pertumbuhan Proliferasi & Diferensiasi SelDocument23 pagesKelainan Pertumbuhan Proliferasi & Diferensiasi SelAidil Fittriani Ayu0% (3)
- Histologi Zukesti1Document4 pagesHistologi Zukesti1milietofathaPas encore d'évaluation
- Sebab-Sebab Kesakitan Dan KematianDocument17 pagesSebab-Sebab Kesakitan Dan KematianmilietofathaPas encore d'évaluation
- PrakDocument12 pagesPrakmilietofathaPas encore d'évaluation
- Morfologi Fungsional SelDocument19 pagesMorfologi Fungsional SelmilietofathaPas encore d'évaluation
- Histologi Zukesti1Document4 pagesHistologi Zukesti1milietofathaPas encore d'évaluation
- Gangguan Saluran NapasDocument1 pageGangguan Saluran NapasImami Rusli PutriPas encore d'évaluation
- Infeksi Saluran Pernafasan AkutDocument8 pagesInfeksi Saluran Pernafasan AkutB'cute DamiaPas encore d'évaluation
- Respiratory FailureDocument24 pagesRespiratory FailuremilietofathaPas encore d'évaluation
- Respirasi 2Document4 pagesRespirasi 2milietofathaPas encore d'évaluation
- Chest ExaminationDocument18 pagesChest ExaminationRahmi Annisa SyarliPas encore d'évaluation
- Morning Sicknes Pada Ibu HamilDocument1 pageMorning Sicknes Pada Ibu HamilmilietofathaPas encore d'évaluation
- Lembar Hasil Pemeriksaan Pasien BatukDocument2 pagesLembar Hasil Pemeriksaan Pasien BatukmilietofathaPas encore d'évaluation
- Respira SiDocument4 pagesRespira SimilietofathaPas encore d'évaluation
- ApoptosisDocument1 pageApoptosismilietofathaPas encore d'évaluation
- Pengaturan Suhu TubuhDocument6 pagesPengaturan Suhu TubuhLili Uisa RahmasariPas encore d'évaluation
- Energi MetabDocument10 pagesEnergi MetabRizuka FathanahPas encore d'évaluation
- Chromosomal Inheritance - Dr. ZulfitriDocument16 pagesChromosomal Inheritance - Dr. ZulfitriSiddiq Muhammad TseloutsenPas encore d'évaluation
- Diare Pada BalitaDocument2 pagesDiare Pada BalitamilietofathaPas encore d'évaluation
- 6th Central Pay Commission Salary CalculatorDocument15 pages6th Central Pay Commission Salary Calculatorrakhonde100% (436)
- Morning Sicknes Pada Ibu HamilDocument1 pageMorning Sicknes Pada Ibu HamilmilietofathaPas encore d'évaluation
- ApoptosisDocument1 pageApoptosismilietofathaPas encore d'évaluation
- Mitosis Dan MeiosisDocument4 pagesMitosis Dan MeiosisYoZa JunNovPas encore d'évaluation
- Pengaruh Derivat Kumarin Dari Kulit BatangDocument5 pagesPengaruh Derivat Kumarin Dari Kulit BatangmilietofathaPas encore d'évaluation
- Kejang DemamDocument11 pagesKejang DemammilietofathaPas encore d'évaluation
- Kebutuhan Cairan Dan ElektrolitDocument13 pagesKebutuhan Cairan Dan Elektrolitapi-383971491% (33)
- Penanda Molekul ApoptosisDocument3 pagesPenanda Molekul ApoptosismilietofathaPas encore d'évaluation
- Brain CancerDocument13 pagesBrain CancermilietofathaPas encore d'évaluation
- 8 EnzymDocument40 pages8 EnzymMecita AfdPas encore d'évaluation