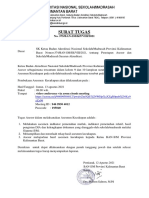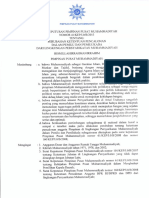Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Am Saefuddin
Transféré par
iansyaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Am Saefuddin
Transféré par
iansyaDroits d'auteur :
Formats disponibles
BAB IV
KARAKTERISTIK EPISTEMOLOGI ISLAM
MENURUT AL-QURAN
Ilmu pengetahuan dalam pandangan al-Quran itu tidak menolak
secara menyeluruh terhadap ilmu pengetahuan Barat. Ada segi-segi tertentu
yang merupakan satu titik persamaan dan perbedaannya. Titik-titik
persamaan itu menunjukkan, bahwa keberadaannya diterima secara
universal. Misalnya, indera diakui oleh al-Quran sebagai salah satu media
untuk
memperoleh
pengetahuan.
Dalam
hal
ini
Ihwan
Al-Shafa
menegaskan, bahwa sesungguhnya seluruh pengetahuan diusahakan,
sedangkan dasar usahanya itu adalah melalui penginderaan. Dan juga
melalui proses pemikiran yang ada pada akal yang mendasarkan pada
lambang-lambang yang dapat diindera.1 Walaupun potensi manusia
tersebut, yakni dalam mengumpulkan fakta sangat terbatas, karena panca
indera memiliki kelemahan yakni dapat keliru dalam melakukan
pengamatan, maka kebenaran ilmiah pun selalu dapat salah atau keliru.
Maka dari itu fakta atau data pun tidak selamanya menampakkan diri
sebagaimana yang ditangkap oleh indera.2
Begitu juga kemampuan akal manusia. Al-Quran mengakui kalau
akal manusia adalah sebagai salah satu sumber atau sarana untuk
mendapatkan pengetahuan. Tetapi sebagaimana indera, akal juga memiliki
kelemahan, sehingga membutuhkan bantuan. Jadi indera dan akal dalam alQuran tidak menolak kalau keduanya adalah sebagai sumber atau sarana
untuk memperoleh pengetahuan. Akan tetapi keduanya tidak bisa disebut
sebagai sumber pengetahuan yang dimutlakkan. Keduanya memiliki
kelemahan dalam memecahkan seluruh persoalan yang dihadapi manusia.
Dikarenakan kondisi keduanya yang serba terbatas itulah, akhirnya dalam
1
Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan
Pemikirannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 31.
2
Mulyadi Kartanegara, Pengantar Epistemologi Islam, (Bandung: Mizan, 2003)
hlm. 21.5
82
83
epistemologi Islam dirancang dan dibangun, di samping mengacu pada
kedua sumber tersebut juga berdasarkan kekuatan spiritual yang bersumber
dari Allah, yakni melalui bantuan wahyu.
Dewasa ini, keprihatinan mulai muncul di kalangan pemikirpemikir Muslim terhadap watak sains modern Barat dan akibat-akibat
yang ditunjukkannya. Sains ini telah dirasakan membahayakan umat Islam
khususnya. Mereka bisa digiring menjadi komunitas yang tidak memiliki
kepekaan sosial. Mereka selalu diarahkan untuk bersikap individual dan
menggunakan parameter-parameter materiil dalam mengukur kebahagiaan
seseorang. Sains tersebut mengalami krisis spiritual yang memprihatinkan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini hanya menonjolkan
kemampuan otak dan ototnya. Sehingga sains yang berkembang sekarang
tidak memiliki konsep dasar Islami, yang mengacu pada al-Quran,
sehingga tidak memiliki kemampuan dalam membendung modernism dan
arus materialisme, yang lebih mengarah pada kemegahan duniawi. Oleh
karena itu Islam secepatnya tanggap pada persoalan pelik tersebut yang
dapat membahayakan umat, khususnya umat Islam, agar tidak terjerumus
pada hal-hal yang tidak dibenarkan ajaran Islam. Penyelamatan tersebut
yaitu membangun ilmu pengetahuan dengan paradigma Islami yang
mengacu pada al-Quran (epistemologi al-Quran).3
Sains yang berkembang harus memiliki nilai-nilai spiritual, dengan
memakai metode intuitif subjektif yang selama ini diremehkan dan
diabaikan. Sebab, menurut aliran positivisme, idealisme, rasionalisme,
intuitif subjektif itu tidak ilmiah dan tidak bisa dipertanggung jawabkan
menurut hukum-hukum logika sekuler. Para ilmuwan sekuler tetap
bertahan pada rasional objektif, sebab ini dipandang paling ilmiah, di mana
manusia sampai pada tahap berpikir positif yang tidak mungkin keliru
menurut logika.4
Mahdi Ghulsyani, Filsafat Sains Menurut al-Quran, (Bandung: Mizan, 1999),
hlm. 108-111.
4
Ibid.
84
Para ilmuwan sekuler begitu gigih memegangi objektivitas sebagai
penentu
validitas
kebenaran
ilmu
pengetahuan.
Sikap
ini
untuk
menghindari adanya pengaruh faktor-faktor luar, seperti; ideologi, tradisi,
kepentingan tertentu maupun agama terhadap penarikan kesimpulan
sebagai kebenaran pengetahuan. Sikap objektif ini sepintas meyakinkan
tetapi ternyata menyisakan sejumlah permasalahan, antara lain: Pertama,
faktor dari luar tersebut tidak selalu salah. Agama Islam misalnya justru
menunjukkan kebenaran kepada manusia melalui al-Quran. Selama ini,
kesalahan terjadi pada sikap dasar ilmuwan Barat itu, bahwa ajaran-ajaran
agama (termasuk Islam) tidak bisa dibenarkan secara ilmiah. Pada
gilirannya agama tidak pernah dipertimbangkan untuk memberikan
masukan-masukan terhadap ilmu pengetahuan. Kedua, dalam sejarah ilmu
pengetahuan ternyata kebenaran ilmiah yang dipandang objektif dan steril
dari pengaruh-pengaruh luar ternyata seringkali digugurkan oleh kebenaran
ilmiah yang juga objektif. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu
yang objektif bisa bertentangan dengan sesuatu yang objektif lainnya
secara berlawanan.
Kelemahan sikap objektif inilah, pengetahuan Islam harus mampu
menampilkan visi lain dalam pemikirannya dengan menghadirkan kekuatan
subjektif yang berasal dari Tuhan untuk membimbing usaha memperoleh
kebenaran ilmu pengetahuan. Sehingga mampu menunjukkan kebenaran
yang bisa diamati, maupun yang tidak bisa diamati oleh indera manusia
atau yang bisa dipikir maupun yang tidak bisa terpikirkan oleh rasio (akal)
manusia. karena kekuatan subjektif ini memiliki wilayah jangkauan yang
selama ini tidak terjangkau oleh potensi manusia. Ini berarti kekuatan
subjektif tersebut jauh lebih tinggi potensinya dari pada kekuatan objektif
manusia. Kekuatan subjektif inilah yang biasa disebut dengan sesuatu yang
transcendental.
Kritik bahwa yang transendental itu tak teramati dan tak terukur,
perlu dijawab dengan pernyataan, bahwa kebenaran itu tidak terbatas pada
yang empirik sensual, seperti dianut positivisme. Manusia adalah makhluk
85
yang lebih dari sekedar bersifat sensual; dia punya akal, punya hati nurani,
dan punya iman.5 Karena dalam keimanan itu tersimpan kekuatan-kekuatan
spiritual yang menakjubkan. Misal seseorang bisa memiliki kesadaran yang
tinggi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, bahkan
penuh resiko, karena dorongan potensi spiritual (iman) tersebut.6
Akal juga terdapat kekuatan spiritual. Akal manusia mempunyai
substansi spiritual yang sumber dan prinsipnya adalah Ilahi atau logos yang
juga merupakan prinsip alam jagat macrocosmic dan merupakan sumber
kitab suci, al-Quran seperti dipercayai oleh kaum Muslim, berada pada
akal Ilahi itu. Akal manusia sebagai individu, alam jagat sebagai
macrocosmic dan al-Quran mempunyai dasar atau sumber metafisika yang
sama-sama memiliki pengaruh besar pada metodologi sains dalam Islam.
Akal tersebut melakukan aktivitasnya yang disebut berpikir. Jika akal
memiliki substansi spiritual, maka dalam berpikir tentu juga dianugerahi
oleh kekuatan spiritual.7
Ibnu Khaldun mengatakan, bahwa sesungguhnya ilmu dan berpikir
itu terjadi dengan sebab adanya kekuatan tertentu dalam diri manusia.
Lantaran adanya ilmu dan berpikir itulah, maka dapat mengembangkan
akal seseorang. Apa yang dikatakan Ibnu Khaldun dengan istilah kekuatan
tertentu dalam diri manusia itu sebenarnya adalah kekuatan yang
dianugerahkan atau kekuatan spiritual. Mestinya manusia menyadari dan
berusaha menghadapkan diri dengan penuh ketundukan kepada Sang
pemberi kekuatan tersebut (Tuhan), bukan malahan sebaliknya berusaha
menghina Tuhan dengan modal kekuatan tersebut, seperti para ilmuwan
dan filosof ateis Barat.8
Berdasarkan realitas spiritual tersebut, tidak mengherankan, jika
Ibrahim
5
Madkour
menuturkan,
bahwa
ada
banyak
filsafat
yang
Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 1998), hlm. 72.
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin,
1992), hlm. 217-218.
7
Endang Saifudin Anshari, Ilmu Filsafat dan Agama, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987),
hlm.149-154.
8
Ibid.
6
86
berlandaskan pada munajat spiritual dan hubungan dengan Allah, maka
Plotinus dalam aliran Iskandariah berpendapat, bahwa ekstase dan emanasi
adalah
kebahagiaan
tertinggi.9
Filosof
yang
menciptakan
ajaran
neoplatonisme yang juga guru dari Porphyrios ini ketika sedang ekstase
bukan hanya sekedar berhubungan dengan Tuhan, melainkan lebih dari itu
dia berusaha menyatu dengan Tuhan yang mirip atau mungkin sama
dengan kasus ittihad dalam kehidupan tasawuf, sebagaimana yang pernah
dialami Abu Yazid Al-Bustami, hulul, al-hallaj, Wahdatul Wujud, Ibn
Arabi dan sebagainya. Penyatuan dengan Tuhan tersebut dirasakan
melebihi segala pengetahuan.10 Sedangkan emanasi dari Plotinus ini
memandang, bahwa semua makhluk yang ada, bersama-sama merupakan
keseluruhan yang tersusun sebagai suatu hirarki. Pada puncak hirarki
terdapat yang satu, yaitu Allah. Teori emanasi ini kemudian berpengaruh
dan diadaptasi oleh AI-Farabi dan Ibnu Sina di kalangan filosof Muslim.
Pengetahuan dalam Islam perolehannya itu lebih didominasi melalui
bantuan kekuatan spiritual, maka baik metode maupun objek pemikiran
ilmu pengetahuan dalam Islam lebih luas dan lebih bervariasi, daripada
yang dialami oleh sains modern Barat. Ilmu dalam Islam di samping tetap
menggunakan metode yang biasa dipakai sains Barat meskipun tidak
seluruhnya, juga memiliki metode sendiri yang tidak dimiliki oleh sains
Barat. Demikian juga objek pemikirannya, di samping terhadap masalah
yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia juga masalah yang tidak mampu
dijangkau. Pada objek yang terakhir inilah peranan kekuatan spiritual
sangat besar, karena akal manusia hanya mampu menerima terhadap
ketentuan-ketentuan yang ada.
Ilmu pengetahuan Islam senantiasa berupaya untuk menerapkan
metode-metode yang berlainan sesuai dengan watak subjek yang dipelajari
dan cara-cara memahami subjek tersebut. Para ilmuwan Muslim dalam
mengembangkan beraneka ragam cabang pengetahuan telah menggunakan
9
Ibrahim Madkour, Filsafat Islam Metode dan Penerapan, terj. Yudian Wahyudi Asmin,
(Jakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 26.
10
K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 9.
87
setiap jalan pengetahuan yang terbuka bagi manusia, dari rasionalisasi dan
interpretasi kitab suci hingga observasi dan eksperimentasi. Penggunaan
metode yang beraneka ragam ini merupakan konsekuensi logis dari realitas
yang dirangkul ilmu pengetahuan Islam. Berbeda dengan sains modern
yang hanya membatasi ruang lingkup pada benda-benda yang bersifat
inderawi (observable facts), ilmu pengetahuan Islam bekerja pada wilayah
yang terpikirkan (conceivable area) dan wilayah yang tidak terpikirkan
(unconceivable area).11 Pada wilayah yang takterpikirkan ini ilmu
pengetahuan dalam Islam banyak diperoleh melalui metode-metode
spiritual yang tidak pernah dipakai oleh sains modern. Menurut M. Riaz
Kirmani, metode spiritual itu terdiri atas intuisi, inspirasi dan mimpi. Fakta
bahwa inspirasi dan mimpi adalah sumber pengetahuan jelas dari alQuran, seperti terkandung dalam Surat Al-Qasas 281: 7 dan Yusuf: 121:
4.12 Maka metode intuisi, inspirasi dan mimpi adalah contoh metode
spiritual, sedangkan sejarah, observasi, eksperimen, penalaran dan
penyimpulan termasuk metode-metode ilmiah (non-Spiritual).
Salah satu ciri utama ilmu pengetahuan Islam, menurut al-Quran
adalah berdasarkan wahyu yang ditempatkan di atas rasio. Wahyu
memperoleh kedudukan yang paling tinggi. Dalam upaya mengembangkan
ilmu pengetahuan Islam, yang akan dilakukan adalah menjadikan wahyu
Ilahi sebagai sumber kebenaran mutlak.13 Suatu kebenaran yang kokoh dan
tidak tergoda dan terbantahkan sedikit pun oleh kebenaran yang lain.
Wahyu Tuhan memberikan penyelesaian terakhir setelah akal tidak lagi
berdaya memecahkan suatu persoalan, tetapi wahyu juga terkadang
memberikan petunjuk awal dari suatu pencarian pengetahuan, sehingga
para ilmuwan untuk melakukan penggalian maupun percobaan ilmiah.
Ringkasnya wahyu menjadi tempat petunjuk dan konsultasi atau sandaran
11
Fuad Nashori, Metode-Metode Perumusan dna Penelitian Psikologi Islam, dalam
Rendra K (peny), Metodologi Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 166.
12
Al-Quran, Juz 1-30.
13
Fuad Nashori, Ibid.
88
bagi ilmu pengetahuan dalam Islam, sehingga posisi wahyu paling
terhormat di antara sumber-sumber pengetahuan yang ada.
Penempatan wahyu pada posisi yang istimewa ini di samping,
karena la adalah ajaran-ajaran Allah sebagai petunjuk kehidupan manusia,
juga sebagai implikasinya wahyu yang mengandung bobot kebenaran
paling tinggi dibanding dengan bobot kebenaran yang dicapai baik melalui
akal (rasio) maupun indera (empirisme). Karena wahyu mencakup
informasi yang tidak terjangkau oleh indera dan akal, sedangkan indera
beraktifitas sebatas yang bisa dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasa.
Di luar itu semua sudah tidak terjangkau lagi oleh indera. Demikian pula
akal bekerja pada sesuatu yang bisa dinalar dan dipikirkan. Di luar itu akal
juga tidak memiliki kemampuan. Padahal banyak kebenaran yang terdapat
pada sesuatu yang berada di luar jangkauan indera maupun akal. Kebenaran
ini hanya bisa diperoleh melalui wahyu. Dengan demikian jelas bahwa
wahyu
memiliki
kedudukan
yang
paling
tinggi
sebagai
sumber
pengetahuan dibanding sumber-sumber pengetahuan lainnya.14
Posisi demikian ini membawa konsekuensi, bahwa menurut
pandangan al-Quran sumber pengetahuan, seperti indera dan akal harus
tunduk pada wahyu. Cara untuk mengenal alam jagat yang menjadi
tumpuhan perhatian pengetahuan atau yang disebut sains, adalah melalui
aktualisasi semua kemungkinan dalam akal itu. Namun, aktualisasi itu
hanya mungkin jika akal tunduk pada kitab suci. Oleh karena itu dipahami
tazkiyah al-nafs (pembersihan jiwa) dalam Islam merupakan satu bagian
integral metodologi untuk memperoleh ilmu. Mereka meyakini bahwa
ajaran-ajaran al-Quran dengan melakukan tazkiyah al-nafs pada saat
memperoleh ilmu atau pengetahuan pasti menghasilkan kebenaran yang
lebih
berkualitas,
daripada
kebenaran
yang
dicapai
akal,
karena
pengetahuan yang diperolehnya tersebut di terima secara langsung dari
Tuhan, baik melalui intuitif, ilham, maupun dalam mimpi karena
kebersihan jiwanya.
14
Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, (Jakarta: UII Press, 1990), hlm. 14-16.
89
Nalar manusia tidak mempunyai posisi yang kokoh untuk
dibandingkan dengan wahyu Tuhan, sebagai petunjuk bagi manusia yang
kebenarannya tidak terbantahkan dalam sepanjang masa.15 Tetapi nalar
manusia dan wahyu Tuhan masih memperoleh korelasi sifat dalam
pandangan yang kita harus menerima fakta-fakta berikut sebagai benar dan
mengandung semua kontroversi yang rumit:
1. Wahyu Tuhan itu tidak dapat diterima, kecuali kalau akal kita
menunjukkan pada intuisi atau keyakinan yang betul-betul bersifat
ketuhanan dan benar.
2. Wahyu Tuhan itu terdiri atas pembicaraan eksternal atau tulisan katakata yang selalu dikonversi ke dalam makna atau masuk ke dalam
perasaan pendengar atau pembaca sebelum mereka dapat dipercaya atau
ditaati.
3. Wahyu memberi pandangan yang benar tentang alam manusia dan alam
semesta, serta intelektual manusia dalam bentuk filsafat yang berusaha
melakukan hal yang sama.16
Dalam hal ini dapat diketahuai bahwa ada keterhubungan antara
akal dan wahyu, hal ini hanya sebatas penjelas, akan tetapi pada taraf
kebenaran, kebenaran wahyu yang transendental lebih tinggi karena
mengandung ayat (bukti), isyarah, huddn (pedoman hidup), dan rahmah.17
Kebenaran wahyu memiliki dua orientasi, yaitu orientasi horizontal
(orientasi yang meletakkan kebenaran yang diperoleh manusia berkaitan
dengan hubungan sesama manusia maupun alam pada umumnya), dan
orientasi vertikal (orientasi dari suatu kebenaran yang diperoleh manusia
dalam hubungannya dengan Allah). Semua kebenaran tersebut ada dalam
wahyu, karena wahyu mewadahi berbagai dimensi kehidupan masyarakat
secara komplek. Wahyu sering menyinggung pengalaman sehari-hari, ilmu
pengetahuan, filsafat, dan sebagainya. Wahyu banyak memberikan pesanpesan intelektual baik berkaitan dengan iman, ritual maupun hubungan
sosial. Dalam wahyu terkandung inspirasi atau benih-benih ilmu
15
Donald B. Calne, Batas Nalar; Rasionalitas dan Perilaku Manusia, (Jakarta:
Gramedia, 2000), hlm. 7
16
Ibid.
17
Mustofa, Sejarah al-Quran, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hlm.29-31.
90
pendidikan, ilmu hukum, sosiologi, sejarah, ekonomi, theologi, biologi dan
sebagainya.
Al-Quran memang bukan buku ilmiah, melainkan buku petunjuk
beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Akan tetapi, al-Quran tampil
memberikan inspirasi atau dorongan kepada para pemikir Muslim,
khususnya untuk membangun ilmu pengetahuan berdasarkan ijtihad mereka
sendiri.
Al-Quran
sengaja
tidak
memberikan
rumus-rumus
ilmu
pengetahuan secara detail dan matang, agar mereka berupaya secara
maksimal menggunakan akalnya dengan petunjuk al-Quran itu untuk
menemukan pengetahuan yang selama ini belum pernah diungkap. Hanya
saja inspirasi ilmiah yang ditunjukkan al-Quran itu mencakup berbagai
bidang keilmuan.18
Dalam al-Quran berisi semua berbagai pengetahuan baik tentang
segala sesuatu yang tampak maupun yang terselubung (gaib) dan berisi
landasan rasional untuk menemukan kebenaran. Untuk memahami pesanpesan yang dikandungnya, Nabi Muhammadlah petunjuk jalannya. Dalam
al-Quran kita menemukan dua macam realitas. Pertama, realitas yang
dapat didekati dengan pengalaman empirik lewat eksperimen dan
observasi. Domain ini terutama yang bertalian dengan sinyal-sinyal AlQuran tentang ayat-ayat kauniyah. Sebagai domain yang dapat dijelaskan
secara empirik, maka di sini penalaran mempunyai posisi yang sangat
strategis dan menentukan. Kedua, realitas yang berada di luar jangkauan
pengalaman inderawi. Ini adalah domain metafisik dan eskatologis. Untuk
domain ini diperlukan pendekatan iman, karena ia merupakan keharusan
metafisik (metaphysical necessity). Realitas tersebut dijadikan objek
pemikiran, sehingga hasilnya memiliki karakter berbeda.19
Pengetahuan yang ditunjukkan oleh wahyu sering dipahami sebagai
kebenaran yang apriori. Kebenaran wahyu sebagai kebenaran yang
diberikan (perennial truth) dan bukan kebenaran yang diupayakan
18
19
Sukanto, al-Quran Sumber Inspirasi, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 9-14.
Ibid., hlm. 1-6.
91
(acquired truth) dengan menggunakan metode ilmiah, serta dapat
dibuktikan secara empirik. Padahal sinyalemen firman (wahyu) sudah
merupakan kesimpulan dari kebenaran yang empiris, dapat dibuktikan.20 Ini
karena wahyu sering mengungkapkan jawaban atas sesuatu sedang
prosesnya
dibebankan
pada
para
pemikir,
ilmuwan
atau
filosof.
Sebagaimana dalam Islam, dalam wahyu tidak ada usaha mencari
kebenaran wahyu, tetapi yang ada adalah usaha mencari bukti kebenaran
itu melalui proses tertentu yang harus ditempuh, karena wahyu itu sendiri
mengandung kebenaran. Hal ini juga yang membedakan dengan tradisi
sains Barat. Dalam sains Barat proses untuk mencapai kebenaran sudah
ada, tetapi kebenarannya itu sendiri belum tercapai. Sebaliknya, dalam
Islam kebenarannya sudah ada, tetapi proses untuk mencari bukti
kebenarannya seringkali tidak dirumuskan.21
Jika pernyataan tersebut menyatakan, bahwa wahyu memberikan
kebenaran apriori ada benarnya dari sudut pengetahuan yang diperoleh
manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah dalam kitab suci. Artinya,
kita mengetahui kebenaran sesuatu berdasarkan informasi wahyu,
walaupun tanpa penelitian atau penggalian lebih dahulu. Tetapi dari sudut
pengalaman bisa juga sebaliknya, yaitu aposteriori artinya kita telah lama
mengalami atau mengamalkan sesuatu ajaran Allah, tetapi belum tahu
rahasia ajaran tersebut dan mungkin kita baru tahu ketentuan-ketentuan
yang memerintahkan untuk mengamalkan sesuatu itu.
Adapun metode pendekatan terhadap wahyu adalah bertitik tolak
dari keyakinan terhadap kebenaran wahyu itu sendiri. Yang dicari bukan
kebenaran baru sebagai alternatif, melainkan pemahaman terhadap
kebenaran mutlak yang terkandung dalam wahyu tersebut. Dengan
menggunakan kemampuan berpikir, manusia diajak untuk mencari
kebenaran yang diperkirakan dapat mendekati kebenaran yang mutlak
tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaannya, pendekatan terhadap
20
21
Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1992), hlm. 4-10.
Ibid.
92
wahyu ternyata tetap menggunakan proses berpikir, meskipun sifatnya
komplementer untuk mencari bukti kebenaran sesuai dengan kandungan
wahyu tersebut. Pada tahapan hasil, pendekatan wahyu langsung
menunjukkan kebenaran tanpa keterlibatan proses berpikir, tetapi pada
tahapan proses untuk membuktikan kebenaran, pendekatan ini tetap harus
menggunakan proses berpikir rasional.
Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan tidak hanya disandarkan
pada sesuatu yang rasional dan empirik semata. Islam menyediakan dirinya
melalui wahyu, Al-Quran dan al-Sunnah, untuk dijadikan acuan dalam
mencari, memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena
itu, Islam tidak hanya merupakan panduan atau petunjuk praktis bagi kaum
Muslim dalam menjalankan ibadah shalat, puasa, zakat, haji dart ibadahibadah mahdah lainnya. Lebih dari itu semua, Islam melalui wahyu Tuhan
dapat dan seharusnya diperankan dalam mewarnai ilmu pengetahuan. Islam
membawa informasi keilmuan dalam jumlah yang banyak dan dapat
dijadikan, baik sebagai inspirasi maupun bahan bagi ilmu pengetahuan.
Apalagi banyak ayat Al-Quran yang menyinggung persoalan alam semesta
beserta isinya untuk diamati secara mendalam. Dari pengamatan itu
diharapkan untuk bisa diperoleh serangkaian pengetahuan.22
Agama memiliki peran dalam memecahkan ilmu pengetahuan.
Beberapa peluang diberikan oleh agama, dan dapat dimanfaatkan oleh ilmu
sosial, yakni dengan meletakkan konsep normatif agama sebagai dasar
perilaku intelektual, dasar bagi epistemologi dan aksiologi ilmu, dan
orientasi pengembangan ilmu (dari proses sampai produk). Melalui agama
seseorang
ilmuwan
dapat
menyandarkan
aktivitas
atau
tindakan
intelektualnya agar tetap terbimbing ke arah yang benar, dapat melakukan
penggalian pengetahuan, dapat memperoleh nilai-nilai yang dapat dijadikan
pertimbangan dan pendampingan dalam kerja ilmiahnya, dan dapat
mengenali seluk-beluk pembentukan ilmu pengetahuan. Pada proses ilmu
ini agaknya sulit direalisasikan, karena biasanya ketentuan wahyu bersifat
22
Ibid.,
93
normatif, bukan teoritis-konseptual. Namun, dalam beberapa contoh
mungkin saja terdapat proses pembelajaran bagi kaum Muslim tentang
bagaimana cara mengembangkan ilmu.23
Dalam kehidupan masyarakat modern seharusnya diperkuat upaya
memperoleh kebenaran agama dan akal agar ada keseimbangan. Berpikir
filsafat dan berpikir ilmiah tidak boleh dibuang dalam kehidupan
masyarakat modern. Akan tetapi manusia juga tidak boleh meninggalkan
kebenaran agama yang datangnya dari Allah Swt. sebagai kebenaran
mutlak yang tidak akan berubah sepanjang zaman. Keseimbangan ini dalam
pandangan
Islam sangat penting agar
tidak terjadi kepincangan-
kepincangan. Keseimbangan ini juga dapat menjauhkan pandangan dan
sikap yang ekstrem ke salah satu pihak dalam kehidupan masyarakat.
Memang Islam memiliki konsep yang dapat diandalkan mengenai
hubungan harmonis antara wahyu (agama) dan akal.
Karakter ilmu dalam Islam yang lain adalah didasarkan hubungan
yang harmonis antara wahyu dan akal. Keduanya tidak dipertentangkan,
karena terdapat titik temu. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam tidak hanya
diformulasikan dan dibangun melalui akal semata, tetapi juga melalui
wahyu. Akal berusaha bekerja
maksimal
untuk
menemukan
dan
mengembangkan ilmu, sedang wahyu datang memberikan bimbingan serta
petunjuk yang harus dilalui akal.24 Maka ilmu dalam Islam memiliki
sumber yang lengkap apalagi ketika dibandingkan dengan sains Barat.
Atas dasar pertimbangan inilah, filsafat dan agama menjadi harapan
dan aspirasi hampir seluruh filosof Muslim. Karena adanya konsep yang
menggambarkan adanya korelasi antara wahyu dan akal, atau antara agama
dengan filsafat (ilmu). Konsep ini memiliki makna yang signifikan
terutama untuk mempertegas, bahwa ilmu dalam Islam memiliki nilai-nilai
transcendental, yakni suatu nilai yang paling tinggi derajatnya.25 Di
23
HAMKA, Filsafat Ketuhanan, (Surabaya: Penerbit Karunia, t.th), 37-40
Ibid., hlm. 25-26.
25
Poerwantana, et, all, Seluk Beluk Filsafat Islam, (Bandung: CV. Rosda, 1988), hlm.
24
110-114.
94
samping itu juga dapat mempertegas, bahwa ilmu dalam Islam tidak
mengenal pertentangan antara wahyu dengan akal.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Kindi seorang filosof Islam,
yang pertama kali menyelaraskan antara agama dan filsafat. Dia melicinkan
jalan bagi Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rusyd.26 Usaha penyelarasan AlKindi ini berperan mengembangkan filsafat sinkretis atau sinkritisme yang
memang memiliki keistimewaan karakter dari sistem yang dimiliki hampir
seluruh filosof Muslim. Mulai dari Al-Kindi inilah mereka berusaha
mengusahakan persesuaian antara agama dan filsafat. Mereka mengajukan
bentuk akidah melalui kesesuaian keduanya.27 Usaha penyelarasan agama
dan filsafat yang dirintis Al-Kindi tersebut tidaklah sia-sia, karena
diteruskan oleh filosof Muslim berikutnya, seperti Ibn Rusyd. Melalui
penafsiran secara rasional, dia mewarnai keselarasan antara agama dan
filsafat. Tradisi pemikiran yang senantiasa menyelaraskan agama dengan
filsafat (ilmu) atau wahyu dengan akal ini terus berlanjut hingga
perkembangan yang terjadi paling akhir sekarang ini di kalangan para
filosof maupun ilmuwan Muslim. Berdasarkan pengamatan mereka
terhadap fungsi wahyu dan akal, maka mereka meyakini sepenuhnya,
bahwa ada titik pertemuan antara keduanya. Keyakinan ini tidak
tergoyahkan sedikit pun mengingat telah jelas fungsi dan peranan masingmasing yang manfaatnya dapat dirasakan bersama. Akal dapat menemukan
kebenaran, apalagi wahyu justru memberikan kebenaran itu tanpa upaya
penelusuran. Sayang sekali Ibn Rusyd gagal menanamkan pengaruhnya
tentang keselarasan antara wahyu dan akal di Barat.
Tradisi pemikiran semacam ini memang tidak biasa terjadi di
kalangan para ilmuwan pada umumnya, terutama para ilmuwan Barat.
Mereka dapat menerima, bahkan menerapkan, bahwa akal sebagai alat
untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan. Namun, mereka menolak
wahyu sebagai alat yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah.
26
27
Ibid., hlm.
Ahmad Fuad al-Ahwani, Filsafat Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 55-56.
95
Maka di kalangan mereka terjadi dikotomi secara tajam antara wahyu dan
akal. Bagi mereka wahyu terlepas dari akal, sedangkan akal sendiri mereka
yakini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan wahyu. Keduanya
bergerak dalam wilayah yang berbeda, sehingga tidak perlu disatukan.
Wahyu bergerak pada wilayahnya dan begitu pula hal yang sama dialami
oleh akal. Jadi, keduanya praktis terputus satu sama lain yang tidak bisa
disatukan.
Dalam kenyataannya, para ilmuwan mengingkari pasangan ilmu dan
agama. Mereka mengambil pesan agama dengan bahasa ilmu. Mereka
hidup dalam keterpecahan sepanjang waktu. Mereka memisahkan bidang
agama dan bidang ilmu, padahal bidang itu pada dasarnya menyeluruh.
Maka oleh para ilmuwan adalah perlawanan antara akal dan agama,
kemudian mereka menciptakan perlawanan antara akal dan perolehan untuk
menjauhkan penglihatan menyeluruh clan hanya berkutat pada bagianbagian. Mereka kurang menyadari, bahwa sesungguhnya ilmu tanpa
didampingi agama akan menyimpang dari akidah yang benar atau
kebablasan, seperti kecondongan mengagungkan akal, sedangkan agama
tanpa didampingi ilmu akan dirasakan sebagai doktrin-doktrin semata yang
membelenggu penalaran dan pemikiran seseorang, karena tidak ada
penjelasan-penjelasan yang memadai dari agama, yang ada hanya
ketentuan-ketentuan normatif.
Mungkin lantaran pengaruh sikap ilmuwan tersebut, hingga
sekarang masih terkesan adanya pertentangan antara agama dan ilmu.
Antara agama clan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan
yang belum serasi. Persoalannya adalah sejauh mana agama dapat
dijangkau oleh jaringan komunikasi ilmiah. Ini menjadi masalah, karena
dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmu
terdapat sikap rasional dan terbuka. Antara agama dan ilmu Pengetahuan
memang terdapat unsur-unsur yang saling bertentangan. Ini yang tampak
dari luar. Namun sebenarnya, jika diamati secara mendasar dalam kondisi
tertentu bisa berkebalikan; dalam ilmu ternyata -terdapat banyak dogma,
96
sedangkan dalam agama masih terdapat sikap rasional dan inklusif. Hanya
saja pandangan dan kesan secara umum memang masih mempertentangkan
antara agama dan ilmu pengetahuan pertentangan ini dapat diungkapkan
secara diantaranya: Kalau dalam bidang agama terdapat sifat statis, di
dalam bidang ilmiah terdapat sikap dinamis, dalam agama itu terdapat
semacam sikap yang tertutup, sedangkan bidang ilmiah sangat terbuka,
kalau dalam agama terdapat sikap emosional sedang dalam bidang ilmiah
terdapat sikap rasional dan sebagainya.
Disamping karakter-karakter tersebut di atas pengetahuan Islam itu
memiliki beberapa orientasi yang dijadikan sebagai tujuan khusus dan
merupakan sebagai bentuk cirikas filsafat pengetahuan Islam. Adapun ciriciri tersebut yaitu:
A. Memiliki Orientasi Teosentris
Berpijak dari suatu pandangan, mengatakan bahwa segala ilmu itu
berasal dari Allah, ini merupakan salah satu perbedaan mendasar antara ilmu
dengan sains, maka implikasinya berbeda sekali dengan sains, ilmu
pengetahuan dalam Islam memiliki perhatian yang sangat besar kepada
Allah. Artinya ilmu tersebut mengemban nilai-nilai ketuhanan, sebagai
nilai yang memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi semua makhluk.
Sebaliknya, ilmu tersebut tidak boleh menyimpang dari ajaran-ajaran
Allah. Jika sains Barat tidak memiliki kepedulian kepada Tuhan, maka
ilmu dalam Islam selalu diorientasikan kepada Allah untuk mencapai
kebahagiaan hakiki.
Oleh karena itu, ilmu dalam Islam tidak hanya semata-mata
berupaya mencapai kemudahan-kemudahan atau kesejahteraan duniawi,
tetapi juga kebahagiaan ukhrawi dengan menjadikannya sebagai sarana
dalam melakukan ibadah. Mahdi Ghulsvani menegaskan, Setiap ilmu
pengetahuan yang kita pelajari adalah merupakan suatu alat untuk
mencapai kedekatan dengan Tuhan, dan tidak mensakralkan suatu ilmu
pengetahuan
yang
diperolehnya,
karena
suatu
pengetahuan
yang
97
diperolehnya tidak selamanya bertahan terhadap apa yang telah diyakini
kebenarannya, dan suatu saat dilemahkan oleh teori baru yang lebih
dipercaya, maka disinilah kita tidak boleh mensakralkan ilmu, apalagi ilmu
itu diperoleh dengan cara pengindraan dan menalar.
Apabila ilmu diperankan untuk mengantarkan kedekatan kepada
Allah memang seharusnya, tetapi tidak perlu dipandang sakral, karena
pandangan ini terlalu jauh dan meanbahayakan. Kita harus menyadari
bahwa tidak semua hal yang mampu mendekatkan kepada Allah bisa
disebut sakral.
Pada tataran penerapan apabila diproyeksikan, bahwa ilmu untuk
ilmu maka tidak memiliki kepedulian kepada lingkungan sekitar.
Selanjutnya
ilmu
hanya
berkaitan
dengan
syarat-syarat
formal
pembentukannya dan prosedur pemakaiannya. Berbeda halnya jika
diproyeksikan ilmu untuk masyarakat, tentu ilmu berupaya mengemban
nilai-nilai pengabdian kepada Allah. Dalam Islam sebenarnya ilmu bukan
hanya untuk ilmu, melainkan yang lebih penting justru untuk kesejahteraan
masyarakat. Dengan begitu, ilmu bisa secara tidak langsung berusaha
mendekatkan
manusia
terhadap
Tuhannya.
Muhammad
Imarah
menyatakan, bahwa ilmu dalam Islam menjadi media menumbuhkan taqwa
kepada Allah. Hal ini berbeda dengan metode dalam ilmu-ilmu lain yang
justru menyebabkan para ilmuwan menghancurkan rasa ketuhanan, bahkan
dengan lantang mereka mengatakan Tuhan telah mati, Ilmu dalam Islam
berupaya membersihkan sikap arogan itu.
Dalam konsepsi keilmuwan Islam, hendaknya dapat dibangun
pengertian, bahwa ilmuwan Islam adalah ilmuwan yang beriman. Dia akan
memandang kenyataan empirik tidak terlepas dari sesuatu yang terletak
dalam alam metafisik. Identitas keagamaan yang melekat pada ilmuwan
Islam dalam mekanisme kerjanya tidak sekadar sebagai sesuatu yang
berada di luar sama sekali. Identitas keagamaan itu dalam realitasnya turut
serta mempengaruhi rangkaian proses pola-pola berpikirnya dalam upaya
mendapatkan pengetahuan. Di sini iman memainkan peranan yang penting
98
sekali. Sidi Gazalba menuturkan, bahwa dalam ijtihad terdapat dialektika
yang dikawal oleh ilmu mantik dan dikendalikan oleh iman. Pembentukan
pengertian, putusan dan penuturan dalam tahap-tahap dialektika itu
dikerjakan oleh ilmu mantik. Sedangkan gerak dialektika itu diarahkan oleh
iman.
Dalam filsafat perennial, berbeda dari filsafat rasionalisme murni,
kepercayaan, pengetahuan, dan kecintaan terhadap Tuhan merupakan
pondasi bagi pengembangan epistemologinya. Betapa pun liberalnya
pemikiran filsafat ketika mengungkapkan ide-ide dan gagasan-gagasan
filosofis, dia tidak akan dengan sengaja dan berani melawan ketentuan
Tuhan secara prinsipil. Artinya pengembaraan nalarnya akan senantiasa
terkontrol oleh ajaran Tuhan.
Ilmu dalam Islam di samping berdasarkan pada fakta empiris dan
akal, juga berdasarkan wahyu (agama). Wahyu mencakup berbagai dimensi
persoalan; mulai dari permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman
atau pengetahuan sehari-hari (knowledge), ilmu pengetahuan (science),
filsafat yang mengandalkan potensi akal, dan persoalan-persoalan supra
rasional (di atas jangkauan akal). Pada persoalan yang terakhir ini, adalah
merupakan wilayah jelajah agama dan di luar jangkauan ilmu maupun
filsafat. Ketika mengemukakan permasalahan yang berkait dengan dimensi
spiritual atau transcendental, maka ilmu dalam Islam juga menggarap
wilayah di luar jelajah ilmu dan filsafat tersebut.
Mattulada menegaskan, Sikap ilmiah seorang ilmuwan yang beriman,
adalah kesadaran yang mendalam, bahwa pada batas terakhir kemampuan
ilmu pengetahuan untuk memecahkan sesuatu, maka disitulah bermula ilmu
yang berpangkal pada iman Islam, diharapkan mampu memberikan jawaban.
Dengan demikian, ilmu dalam Islam berlapis ganda; lapis indera, lapis akal,
dan lapis iman. Oleh karena itulah ilmu dalam Islam memiliki kandungan
informasi dan pembahasan yang jauh lebih mendalam daripada sains, karena
ilmu dalam Islam di samping melalui proses yang biasa dilalui oleh sains juga
mendapatkan bahan-bahan informasi dari Tuhan melalui wahyu. Dengan kata
99
lain, ilmu dalam Islam memiliki sesuatu yang dimiliki dan sesuatu yang tidak
dimiliki oleh sains. Di sinilah letak kelebihan atau keunggulan ilmu dalam
Islam dibanding sains.28
Adapun keunggulan itu terletak pada faktor transendental. Sains Barat
yang masih ditandai oleh sikap-sikap intelektual dan intelektualistis, tidak
menghargai transendensi. Sebaliknya dalam banyak kebudayaan Timur,
transendensi tidak saja diakui, tetapi bahkan dianggap sebagai sesuatu yang
pencapaiannya perlu diusahakan oleh setiap insan. Dalam konteks Islam,
secara epistemologis, sumber segala ilmu itu transendental. Untuk menjaga
pikiran, kearifan dan kesucian ilmu-ilmu yang intransendental perlu
dikonsultasikan kepada yang transendental. Sebaliknya kita menggunakan
yang transendental secara reflektif, suatu upaya mondar-mandir antara
induksi-deduksi hampir setiap saat. Upaya ini tidak berdampak pada
perubahan yang intransendental menjadi transendental, tetapi dengan
harapan bahwa yang intransendental itu sedapat mungkin terilhami atau
tersinari oleh nilai-nilai transendental, sehingga perkembangannya masih
dalam kontrol pesan-pesan Tuhan.
Ilmu pengetahuan dalam Islam bersifat universal yang menyatu
dengan nilai-nilai Ilahiyah atau Ketuhanan. Maka keberagamaan atau
keimanan seseorang dalam ajaran Islam meliputi pernyataan tiga komponen
yang ada pada diri manusia, yakni hati nurani atau kalbu (tasdiq bi alqalb), lisan (iqrar bi al-lisan), dan perbuatan (`alnal bi al-arkan) yang
saling melengkapi satu sama lainnya. Umat Islam patut bersyukur, karena
ada tempat konsultasi yang lebih, daripada kebenaran etik insanivah,
yaitu kebenaran integratif ilahiyah. Hal ini disebut kebenaran integratif
ilahiyah, karena kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadits
memberikan kepada manusia berupa ayat, isyarat, hudan dan rahmah.
Kebenaran ilahiyah merupakan kebenaran tertinggi, di atas
kebenaran tersebut tidak ada lagi kebenaran. Kebenaran inderawi,
28
Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga
Metode Kritik, (Jakarta, Erlanga, t.th), hlm. 156
100
kebenaran akal (i]mu dan filsafat) semuanya merupakan kebenaran nisbi.
Tapi kebenaran ilahiyah merupakan kebenaran mutlak atau kebenaran
hakiki. Agar ilmu dan filsafat tidak terjebak dalam kesalahan yang fatal
perlu menyandarkan kepada kebenaran ilahiyah.
Kebenaran
ilahiyah dalam tradisi keilmuwan
Islam selalu
ditempatkan pada posisi yang tertinggi, karena berfungsi memantau
terhadap kebenaran-kebenaran di bawahnya, seperti kebenaran yang
dicapai indera maupun akal. Dengan indera dan akal para ilmuwan
Muslim melakukan kegiatan ilmiahnya, sedang untuk menentukan
persoalan-persoalan yang pelik yang sekiranya tidak terjangkau oleh
indera dan akal, biasanya mereka langsung merujuk pada kebenaran
ilahiyah yang terungkap dalam wahyu (Al-Quran dan al-Hadits). Metode
semacam ini telah dimulai dari generasi paling awal hingga generasi
terakhir ini. Memang seharusnya kebenaran ilahiyah selalu menjadi
sandaran bagi segala ilmu pengetahuan ilmiah. Dalam istilah lain
Ziauddin Sardar menyebut kebenaran ilahiyah itu dengan istilah Kerangka
Pedoman Mutlak. Dalam hal ini Ziauddin Sardar, mengemukakan bahwa
semua teori pengetahuan yang tidak mengandung Kerangka Pedoman
Mutlak hanya dapat menjurus kepada pertentangan dan kekacauan; tidak
ada kebenaran-kebenaran objektif yang dapat ditemukan lewat akal
semata.29
Kebenaran ilahiyah atau menurut Ziauddin Sardar dengan istilah
Kerangka pedoman Mutlak itu secara jelas dan tertulis ditemukan dalam
Al-Quran. Para ilmuwan Muslim selalu merujuk pada al-Quran itu.
Menurut Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid All Asyraf, Al-Quran
merupakan petunjuk jalan bagi cendekiawan Muslim dalam hal cara
berpikir, terutama mengenai tiga aspek pokok ilmu pengetahuan: aspek
etik, termasuk aspek-aspek perseptual dalam ilmu pengetahuan; selanjutnya
mengandung aspek-aspek historis dan psikologik dalam ilmu pengetahuan;
29
Ibid., 157
101
dan aspek-aspek observatif dan eksperirnental dalam ilmu pengetahuan.30
Ketiga cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu menurut Muhammad
Iqbal merupakan satu-satunya alat untuk menempatkan prinsip tauhid
sebagai faktor yang berperan dalam kehidupan intelektual dan emosional
manusia, yang merupakan landasan spiritual Islam tertinggi. Oleh karena
itu, tauhid lebih jauh harus diperankan dalam mengendalikan, mengontrol
dan mengarahkan kecenderungankecenderungan nalar manusia yang
selama ini condong bebas dan tak rnau terikat oleh siapa pun, yang hanya
mengandalkan pada kekuatan akal (rasio) dan indranya.
B. Terikat Nilai
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengetahuan Islam itu
dipengaruhi oleh dimensi spiritual, wahyu, intuisi, dan memiliki orientasi
teosentris, konsekuensi berikutnya sebagai salah satu ciri ilmu tersebut
adalah terikat nilai. Ini sangat membedakan dengan sains Barat karena
semangat tradisi ilmiah Barat senantiasa berusaha menegaskan, bahwa ilmu
itu netral atau bebas nilai, tidak boleh terikat nilai tertentu. Bahkan
menurut pandangan Barat, salah satu syarat keilmiahan adalah bersifat
objektif. Sifat objektif ini berarti menyatakan fakta apa adanya dan tidak
boleh dipengaruhi oleh fakta apa pun.
Pengetahuan tidaklah netral dan memang dapat dimasuki suatu sifat
dan muatan yang ditopangi sebagai pengetahuan. Menurut epistemologi
Kuhn, sebuah sains yang objektif, bebas nilai dan netral, tidak mungkin
akan ada. Demikian juga, konsep bebas nilai dalam penelitian ilmiah, yang
diagung-agungkan oleh Max Weber, tidak lebih, daripada mitos, hanyalah
impian yang indah. Ketika seseorang ilmuwan merumuskan teori-teori
sebagai hasil dari penelitiannya tidak mungkin secara utuh disampaikan
sesuatu yang benar-benar netral dan bebas nilai.
Ada banyak faktor yang turut mempengaruhi rumusan teori tersebut,
sebab para ilmuwan sendiri tidak mungkin hidup di alam terlanjang. Profil
30
Ibid., 158
102
seorang ilmuwan itu akan dibentuk oleh pengaruh pengaruh yang diserap
selama hidupnya. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa berbentuk agama,
ideologi, faham, latar belakang pendidikan, profesi, teori-teori pengetahuan
yang dikuasai, paradigma berpikir dan sebagai nya. Pengaruh-pengaruh
tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik disengaja
maupun kebetulan akan turut mewarnai hasil kerja ilmiah seseorang
ilmuwan termasuk menyangkut teori-teori ilmiah yang dirumuskannya. Dia
tidak bisa menghindar dari pengaruh-pengaruh itu, karena seringkali
muncul di luar kesadaran dirinya. Contoh yang paling sederhana, jika
seorang ilmuwan dalam mengungkapkan teori-teori ilmiah dengan
menggunakan pola berpikir atau pendekatan tertentu dari ilmuwan lain,
padahal pola berpikir dan pendekatan itu mengandung kelemahankelemahan, sementara itu ilmuwan lainnya lagi memiliki pola pikir dan
pendekatan yang berbeda sama sekali. Ini berarti pola pikir dan pendekatan
dari ilmuwan lain yang dipakai itulah yang mempengaruhi jalan
pikirannya, dan tentu juga berpengaruh sampai pada hasil pemikirannya
yang disebut bebas nilai itu.
Para ilmuwan tidak mungkin mampu membersihkan dirinya sendiri
dari
pengaruh-pengaruh
tersebut
ketika
memproses
suatu
ilmu
pengetahuan. Apalagi jika yang menjadi objek penelitian berupa pelaku,
pemeran, atau subjek, seperti manusia, tentu para ilmuwan tidak akan
mampu berdiri di tengah-tengah tanpa adanya keterpengaruhan. Oleh
karena itu, Hidayat Nataatmadja menegaskan, bahwa pendekatan objektif
mustahil bisa dipakai untuk memperoleh ilmu yang benar mengenai
manusia sebagai subjek. Untuk mengenal manusia sebagai subjek tidak ada
jalan lain, kecuali menggunakan ilmu supra-subjektif, ilmu mengenai
subjek.31 Antara karakter sasaran penelitian untuk dikenali secara cukup
mendalam dengan sarana yang dipakai mengenali terdapat kesamaan,
31
Hidayat Naatmadja, Membangun Ilmu Pengetahuan dengan Ideologi, (Bandung: Iqra,
1983), hlm. 19.
103
sehingga relatif lebih memudahkan proses pengenalan, daripada karakter
antara keduanya kontras.
Hidayat Nataatmadja memberi kepastian bahwa ilmu supra-subjektif
ini memiliki validiras yang lebih tinggi dibanding ilmu-ilmu objektif. Ilmu
supra-subjektif dihasilkan melalui pertimbangan yang lebih mendalam
(menyangkut fakta dan di balik fakta), daripada ilmu-ilmu objektif yang
hanya mendasarkan pada fakta empiris. Berdasarkan alur pemikiran
tersebut ilmu pengetahuan yang selalu bersifat netral dan tidak memihak
dalam masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan mulai digugat oleh
anak cucu renaissance dan Aufklarung sendiri. Teori ilmu objektif, yang
dikembangkan oleh orang-orang, seperti Descartes dari masa lampau dan
Popper dari masa sekarang, terus-menerus digugat. Oleh karena itu, klaim
ilmu pengetahuan yang netral bebas nilai dan objektif terpaksa
menyebabkan manusia modern lama melihat manusia dan lingkungan
sebagai objek semata. Suatu objek yang bisa dimanipulasi kembali dengan
rekayasa mereka, sehingga orang mulai tertarik kembali kepada etik, yaitu
etika pada aspek praktisnya, bukan pada aspek teorinya.32
Ketika sebagai nilai dapat memberikan penghargaan yang tinggi
kepada manusia dan lingkungannya dengan peranannya bukan saja sebagai
objek, melainkan yang lebih penting justru sebagai subjek. ketika ini tidak
diperhatikan dalam tradisi keilmuwan Barat, sehingga Barat mampu
mencapai kemajuan sains dan teknologi, namun kemajuan tersebut
sesungguhnya semu dan mengalami kepincangan mengingat dalam waktu
yang bersamaan menimbulkan dekadensi moral yang sangat parah. Orangorang Barat merasa resah terhadap dampak negatif dari serangkaian
kemajuan yang berhasil dicapai. Kondisi demikian secara langsung maupun
tidak langsung adalah akibat dari sains mereka yang tidak dibangun di atas
landasan etika. Jika saja ketika dijadikan landasan bagi bangunan sains
mereka, setidaknya mampu mengendalikan, bahkan mencegah timbulnva
krisis moralitas tersebut.
32
Ibid.,hlm.20-21.
104
Berbeda dengan tradisi Barat tersebut, tradisi keilmuwan Islam
sejak dini memiliki perhatian besar pada mereka. Pada prinsipnya ketika
diyakini memiliki peranan yang besar dalam menuntun perkembangan
pengetahuan
dan
respons
masyarakat,
sehingga
pertimbangan-
pertimbangan aksiologis selalu ditempatkan menyertai pertimbanganpertimbangan episternologis, agar di samping mampu mencapai kemajuan
juga mampu mempertahankan keutuhan moralitas yang positif. A. Rashid
Moten menegaskan, dalam Islam ilmu harus didasarkan nilai dan harus
memiliki fungsi dan tujuan. Dengan kata lain, pengetahuan bukan untuk
kepentingannya sendiri, tetapi menyajikan jalan keselamatan, dan agaknya
tidak seluruh pengetahuan melayani tujuan ini. Sains-sains sosial dan
humanika jelas relevan terhadap nilai-nilai, sebaliknya nilai-nilai adalah
relevan dengan mereka. Ini tidak berarti bahwa sains-sains tersebut adalah
subjektif, walaupun subjektivisme seringkali masuk ke dalamnya, kadangkadang dengan jelas dapat dirasakan. Jelasnya, sains yang berorientasi nilai
tidak berarti subjektif, asal nilai-nilai tersebut tidak diam semata-mata
sebagai asumsi-asumsi, tetapi diobjektifkan.
Pentingnya nilai mendasari ilmu tersebut pada bagian lain juga
untuk kesejahteraan dan kekuatan manusia. Hanya dengan menempatkan
manusia sebagai subjek, maka manusia dapat memanfaatkan ilmu secara
optimal. Bila manusia ditempatkan sebagai objek maka dia tidak akan
mampu berperan secara leluasa dan derajatnya tidak lagi terhormat, seperti
dalam persepsi ilmuwan Barat. Barangkali tidak banyak ilmuwan Barat,
seperti Francis Bacon. Dia menyarankan, pengetahuan itu harus dapat
mendatangkan keuntungan bagi manusia, artinya la harus dapat dipakai
untuk meningkatkan kemampuan dan memperbesar kekuasaan manusia.
Francis Bacon seperti berupaya untuk mengingatkan para ilmuwan agar
bersikap memandang ilmu untuk kepentingan manusia, dan peringatan ini
agaknya untuk meluruskan fenomena yang sedang berkembang di Barat,
bahwa justru sebaliknya manusia untuk kepentingan ilmu, sehingga hanya
dipandang sebagai objek bagi proses kegiatan ilmiah. Memang banyak
105
disiplin ilmu yang objek materialnya adalah manusia, tetapi secara
keseluruhan manusia harus diperankan sebagai subjek dengan pengertian,
bahwa dialah yang memanfaatkan ilmu.
Maka dari itu, ilmu seharusnya selalu didasari nilai agar selamat
dari penyelewengan. Namun, ada juga pandangan yang moderat dengan
mengadakan pembagian antara wilayah yang bebas nilai dan penuh nilai.
Jujun S. Suriasumantri menjelaskan, bahwa ontologi dan epistemologi
keilmuwan mempelajari sains sehingga mengkaji alam sebagaimana adanya
yang berisi nilai. 33 Tetapi bagaimana dan untuk apa ilmu itu dipergunakan.
Ini berorientasi kepada das sollen (bagaimana seharusnya) yang sarat
dengan nilai yang bersifat etis. Sedangkan Asghar All Engineer menilai,
Aql bebas nilai, sebaliknya `ilm dan hikmah dibebankan dengan nilai-nilai
positif, nilai-nilai yang menggerakkan keinginan emosi untuk maju dan
berubah secara sehat untuk mengurangi tingkat kejahatan di dunia ini.
Persoalannya adalah jika akal bebas nilai sedang ilmu sarat nilai, kemudian
bagaimana ketika ilmu itu dihasilkan oleh akal. Apakah ilmu tersebut tetap
sarat nilai atau berubah menjadi bebas nilai mengikuti akal. Tampaknya
pembagian wilayah yang diutarakan Asghar Ali Engineer tersebut agak
mudah dipahami, jika dimaknai bahwa ketika ilmu tersebut dirumuskan,
maka ada akses bagi pertimbangan-pertimbangan nilai. Sementara itu akal
berpikir apa adanya sesuai dengan aslinya.34
Kitab suci Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan
pedoman hidup umat Islam terdapat banyak macam nilai, terutama jika
diamati, bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya kebanyakan
bersifat normatif sesuai dengan kapasitasnya sebagai kitab petunjuk, bukan
kitab ilmiah, meskipun ada banyak pernyataannya yang memberikan
informasi dan sekaligus inspirasi untuk membangun ilmu pengetahuan.
Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran tentu penuh dengan nilai-nilai.
33
Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1990), hlm. 105-108.
34
Inu Kencana Syafiie, Al-Quran dan Ilmu Politik, (Jakarta: Rineka Cipta: 1996), hlm.
14-23 .
106
Demikian juga yang terjadi pada hadist shahih. Mengenai nilai ini dalam
seminar di Stockholm pada 1981 tentang Pengetahuan dan Nilai
diidentifikasi 10 konsep yang menggeneralisasikan nilai-nilai dasar kultur
Islam: tauhid, khilafah, ibadah, ilm, halal dan haram, `adl, zulm, istislah dan
diya. Nilai-nilai in masih bisa diperdalam lagi secara detail dan
dikembangkan secara spesifik, jika diinginkan untuk menggalinya. Dengan
kata lain bahwa kitab suci sangat terikat nilai karena kitab suci adalah
pedoman hidup manusia.
Vous aimerez peut-être aussi
- Format DU & F 2.2Document58 pagesFormat DU & F 2.2iansya100% (2)
- Simulasi Penilaian SMK-MAKDocument169 pagesSimulasi Penilaian SMK-MAKiansyaPas encore d'évaluation
- Surat Tugas Asesmen Kecukupan BAN-SM Prov - kalbAR Tahun 2021.Document15 pagesSurat Tugas Asesmen Kecukupan BAN-SM Prov - kalbAR Tahun 2021.iansyaPas encore d'évaluation
- Perubahan Jadual Asessmen Kecukupan BAN-SM Prov - Kalbar 2021Document1 pagePerubahan Jadual Asessmen Kecukupan BAN-SM Prov - Kalbar 2021iansyaPas encore d'évaluation
- Undangan Pembekalan Asesor BAN-SM Prov - KalbarDocument9 pagesUndangan Pembekalan Asesor BAN-SM Prov - KalbariansyaPas encore d'évaluation
- Undangan Visitasi Tahun 2021Document2 pagesUndangan Visitasi Tahun 2021iansyaPas encore d'évaluation
- Surat Pernyataan Kembali MengabdiDocument1 pageSurat Pernyataan Kembali MengabdiiansyaPas encore d'évaluation
- 9776169Document17 pages9776169iansyaPas encore d'évaluation
- SK Pemilu PilkadaDocument3 pagesSK Pemilu Pilkadaiansya100% (1)
- Bank FahmilDocument103 pagesBank FahmiliansyaPas encore d'évaluation