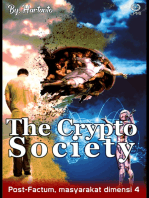Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Anom Astika Politik Perjuangan Intelektual
Transféré par
Pras PrasojoCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Anom Astika Politik Perjuangan Intelektual
Transféré par
Pras PrasojoDroits d'auteur :
Formats disponibles
03.06.
2011 15:34
Politik Perjuangan Intelektual
Penulis : I Gusti Agung Anom Astika*
Indonesia dengan segala keragamannya memang bukan sesuatu yang mudah dipahami.
Dari segi kewilayahan saja, begitu sengit debat di antara para pendiri bangsa ini terutama dalam perdebatan antara Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin dalam risalah sidang BPUPKI tahun 1945. Yamin berpendapat, Indonesia adalah seluruh wilayah kuasa Majapahit, sedang Hatta berpendapat Indonesia adalah wilayah bekas jajahan kolonial Hindia Belanda. Dua puluh delapan tahun sebelumnya terjadi perdebatan antara Soeriokoesoemo dengan Liem Hian Koen tentang siapa yang bisa disebut sebagai orang Indonesia, atau bangsa Hindia menurut istilah mereka pada tahun 1917. Tjipto Mangoenkoesoemo menjawab saling silang pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa dasar dari adanya bangsa ini adalah persamaan kepentingan politik di dalam melawan kolonialisme. Artinya tidak penting latar etnisitas membatasi kepentingan pembentukan bangsa, sepanjang latar belakang itu justru menyediakan syarat bagi tumbuhnya kesadaran anti kolonialisme. Apa alasannya? Jawab Tjipto, "kata bangsa Hindia ini termasuk juga peranakan Eropa dan juga peranakan Tionghoa. Mereka ini sesudah dilahirkan di bawah lambaian nyiur lebih banyak dibesarkan oleh babu Sarinah daripada oleh ibunya sendiri, belum lagi disebutkan hal-hal yang acapkali terjadi, yaitu mereka yang dikandung dan dilahirkan oleh babu Sarinah yang itu juga". Selintas mungkin yang dinyatakan Tjipto seumpama desas-desus rahasia umum masyarakat pada masa itu. Tetapi seandainya mereka yang dilahirkan itu adalah orang-orang yang lebih akrab dengan kebudayaan Indonesia, dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah di Indonesia, lalu mengerti apa akibat buruk dari kolonialisme, tidak ada dasar untuk menjadikan mereka bukan Indonesia. Sehingga sekali lagi memang tidak sederhana untuk sekedar berpikir tentang Indonesia. Memasuki periode kemerdekaan,persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa yang baru merdeka ini pun juga semakin banyak. Tidak sekadar tentang bagaimana membangun pemerintahan yang berdaulat, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, tetapi juga perihal membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Ini mengingat bahwa salah satu poin hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia diwajibkan menanggung beban biaya perang Belanda di Indonesia. Sementara kekuatan industri belumlah tumbuh dan sejumlah organisasi massa sektoral belum mampu mentransformasikan dirinya menjadi organisasi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi nasional.
1/3
Melahirkan Kekerasan Di tengah situasi ini, krisis ekonomi-politik yang melahirkan kekerasan demi kekerasan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Realitas yang demikian ini berlangsung hingga puncaknya pada kekerasan yang terjadi pada tahun 1965. Sebuah realitas yang membumihanguskan seluruh capaian kesadaran politik sejak awal kemerdekaan, demi kepentingan kekuatan politik tertentu dalam mengupayakan pembangunan ekonomi berbasis modal internasional. Sebuah realitas yang mengajarkan kepada kita semua, bahwa sangat mungkin dan tersedia syarat-syaratnya untuk adanya gelombang kekerasan demi kekerasan untuk pemenangan tujuan politik tertentu. Bahkan jika direfleksikan pada sejarah Orde Baru, dan perkembangan 13 tahun reformasi, maka fenomena kekerasan terhadap rakyat itu bukan lagi kecelakaan, tetapi metode, cara, strategi taktik untuk memuliakan politik, dalam maknanya yang paling banal, kekuasaan. Berbasis pada gambaran ringkas kenyataan sejarah yang sudah ditampilkan, maka sebenarnya tidak ada persoalan mendasar yang perlu dibedakan antara tulisan ini dengan pendapat Ahan Syahrul dalam opininya Amanat Kaum Intelektualyag diturunkan harian ini tanggal 27 Mei 2011, menanggapi tulisan saya sebelumnya. Semua yang dikatakan olehnya, adalah benar adanya. Termasuk juga kategori-kategori tentang siapa-siapa yang pantas disebut sebagai intelektual, dengan segala keutamaannya. Persoalannya, segala bentuk keutamaan intelektual yang tersedia dalam bentuk nilai-nilai itu tidak akan mempunyai kemampuan, atau bahkan potensi, untuk menjawab berbagai bentuk persoalan masyarakat yang tersedia pada saat ini. Sebagai contoh misalnya dalam kasus kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP di Jakarta beberapa waktu lalu. Banyak dari kalangan intelektual, atau bahkan kalangan yang mengenyam pendidikan hingga ke bangku perguruan tinggi, sampai yang bersekolah ke luar negeri, dengan cepat berpendapat, Bubarkan Satpol PP. Alasannya sederhana, karena sudah berulang kali Satpol PP melakukan kekerasan terhadap masyarakat bawah, sehubungan dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk menertibkan sejumlah kawasan. Pendapat itu mungkin benar, jika dilihat dari perspektif anti kekerasan, perspektif humanisme yang kini sedang giat dibangun oleh kalangan intelektual, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat. Persoalannya, siapa itu Satpol PP, dan siapa-siapa yang direkrut ke dalam Satpol PP. Sampai dengan saat ini belum pernah ada studi yang cukup teliti dan serius tentang upaya-upaya pembentukan organ-organ kekerasan yang berlangsung pada periode reformasi. Secara amatan sekilas, sudah kelihatan jelas bahwa mereka yang direkrut ke dalam Satpol PP adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah bawah juga. Sehingga apabila kaum intelektual ini menyatakan Bubarkan Satpol PP apakah itu berarti juga bahwa kaum intelektual akan dapat menanggung hidup dan nafkah dari mantan anggota Satpol PP setelah itu badan itu dibubarkan? Mendengarkan Masyarakat Letak soalnya bukan pada pendefinisian intelektual, apakah mereka terdidik secara sekolahan ataupun yang
2/3
tidak terdidik secara sekolahan. Bahkan bukan juga pada nilai nilai semacam apa yang sedang mereka perjuangkan. Tetapi apakah dalam politik itu selalu mengandaikan nilai? Dalam tataran fenomenologis bisa dijawab 'ya'. Tetapi dalam tataran praktis, maka segala bentuk nilai itu akan dan harus melebur pada upaya-upaya metodologis. Dengan kata lain untuk mengerti persoalan-persoalan masyarakat tidak bisa dimulai dengan berkhotbah ataupun berceramah tentang pentingnya nilai nilai kejujuran dan keadilan. Tetapi mulailah berbicara kepada masyarakat, dan mulailah mendengarkan segala bentuk cerita masyarakat mengenai apa apa yang mereka alami sehari hari. Melihat kenyataan itu sendiri, mempelajarinya, sebagai dasar untuk merumuskan apa persoalan-persoalan masyarakat, untuk kemudian bersama dengan masyarakat mencari jalan keluarnya. Dalam realitas masyarakat yang tersedia pada saat ini, segala bentuk persoalan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dialami oleh masyarakat, selalu memiliki kaitan dengan kepentingan-kepentingan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Artinya upaya untuk menyelidiki persoalan-persoalan masyarakat juga mengandaikan adanya dialog-dialog dengan berbagai macam kekuatan politik. Tidak jamannya lagi menjadikan segala sesuatu yang mengerikan di masa lalu, sebagai yang betul betul mengerikan di masa kini. Tetapi berupaya melihat segala sesuatunya dalam kerangka politik sebagai upaya mengorganisasikan pikiran. Mengapa demikian, karena bagaimanapun pengetahuan yang dimiliki oleh kaum intelektual dari manapun itu asalnya, ketika diterjunkan, didaratkan ke kehidupan sehari-hari masyarakat, baru menjadi penting bagi masyarakat ketika masyarakat menyadari, bahwa mereka telah melahirkan pengetahuan yang baru bagi dirinya. Pengetahuan yang menjawab persoalan-persoalan mereka. Demikianlah makna dari praksis. *Penulis adalah Mahasiswa STF Driyarkara.
3/3
Vous aimerez peut-être aussi
- Tugas PaperDocument7 pagesTugas Papersofia sembiringPas encore d'évaluation
- ISU POLITIKDocument7 pagesISU POLITIKRamadaniPas encore d'évaluation
- Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Bung HattaDocument5 pagesPemikiran Ekonomi Kerakyatan Bung HattaJonedi B. ManaluPas encore d'évaluation
- Pendidikan DemokrasiDocument10 pagesPendidikan DemokrasiNal DiPas encore d'évaluation
- Ilmu PolitikDocument6 pagesIlmu PolitikAyu DantiAPas encore d'évaluation
- Peran Generasi Muda Bagi BangsanyaDocument13 pagesPeran Generasi Muda Bagi BangsanyaAli Murtadlo100% (1)
- Implementasi NilaiDocument7 pagesImplementasi NilaiJaya Putra NegaraPas encore d'évaluation
- UTS PANCASILA - Amanda Ayu RamadhaniDocument3 pagesUTS PANCASILA - Amanda Ayu RamadhaniAmanda AyuPas encore d'évaluation
- SISTEM POLITIK INDONESIADocument8 pagesSISTEM POLITIK INDONESIARicki Pratama PutraPas encore d'évaluation
- Gerakan HAM Masa KiniDocument23 pagesGerakan HAM Masa KiniABINOAK GOBAI 1Pas encore d'évaluation
- Ancaman Di Bidang PolitikDocument5 pagesAncaman Di Bidang PolitikfannyirfanPas encore d'évaluation
- Jurnal Konflik Sosial BantenDocument17 pagesJurnal Konflik Sosial Bantenalmaarhief07100% (1)
- Penjelasan Setiap Slide SosialisaiDocument6 pagesPenjelasan Setiap Slide SosialisaiRita Lombu'uPas encore d'évaluation
- Ri Bab 2Document7 pagesRi Bab 2lumbangaolnaomiPas encore d'évaluation
- (FIX) Nasionalisme Kehabisan TenagaDocument32 pages(FIX) Nasionalisme Kehabisan TenagaDicky arisPas encore d'évaluation
- MENGHENTIKAN RASISMEDocument2 pagesMENGHENTIKAN RASISMEAdrian Diko AnanthoPas encore d'évaluation
- Harmonisasi Hak dan KewajibanDocument7 pagesHarmonisasi Hak dan KewajibanMuhamad Qeisya HanifPas encore d'évaluation
- ESSAI SOSIO-TEKNOLOGI DALAM MENGHADAPI GEMPURAN ZAMAN (Yoga Wicaksono)Document11 pagesESSAI SOSIO-TEKNOLOGI DALAM MENGHADAPI GEMPURAN ZAMAN (Yoga Wicaksono)brilli'am santosoPas encore d'évaluation
- Triangle DemokrasiDocument16 pagesTriangle DemokrasiInsyafani Muhamad SidiqPas encore d'évaluation
- Tugas PPKN 4.1 Hal 112Document2 pagesTugas PPKN 4.1 Hal 112faniaaa triwidyantii71% (7)
- Uts PKN YolandaDocument4 pagesUts PKN YolandaYolanda Yosevina TariganPas encore d'évaluation
- Materi PancasilaDocument111 pagesMateri PancasilayohanismariovianytualakaPas encore d'évaluation
- Materi PancasilaDocument46 pagesMateri PancasilayohanismariovianytualakaPas encore d'évaluation
- Civil Society Di IndonesiaDocument7 pagesCivil Society Di IndonesiaIlham AinuddinPas encore d'évaluation
- BAB 4 PancasilaDocument8 pagesBAB 4 PancasilaTri WulandariPas encore d'évaluation
- HAM SEBAGAI ISU GLOBALDocument8 pagesHAM SEBAGAI ISU GLOBALAzham Reeza100% (1)
- Kajian Permasalahan Kebangsaan dan Solusinya melalui Pemikiran Tokoh Pendiri BangsaDocument3 pagesKajian Permasalahan Kebangsaan dan Solusinya melalui Pemikiran Tokoh Pendiri Bangsafaqih fahroziPas encore d'évaluation
- Makalah Pendidikan KewarganegaraanDocument19 pagesMakalah Pendidikan KewarganegaraanAldilla SaadyPas encore d'évaluation
- S1 SKRIPSI - PUBLIC 2007 Anggraini - Miftachur - Rochmah CompleteDocument113 pagesS1 SKRIPSI - PUBLIC 2007 Anggraini - Miftachur - Rochmah CompleteMahakPas encore d'évaluation
- Budaya Politik UnggulDocument4 pagesBudaya Politik UnggulDenny Pe EMPas encore d'évaluation
- Sosiologi A1 - Alfina Nur Rohmah - 200910101023Document4 pagesSosiologi A1 - Alfina Nur Rohmah - 200910101023Alfina Nur RohmahPas encore d'évaluation
- Ketahanan Nasional Bidang PolitikDocument9 pagesKetahanan Nasional Bidang PolitikPrafitri KurniawanPas encore d'évaluation
- Masyarakat MadaniDocument56 pagesMasyarakat MadaniJenny ValentinPas encore d'évaluation
- Masalah Nasionalisme Dan PatriotismeDocument5 pagesMasalah Nasionalisme Dan PatriotismeapprorPas encore d'évaluation
- SOAL UAS PKNDocument4 pagesSOAL UAS PKNRahma WatiPas encore d'évaluation
- Modernisasi Politik - Kel DPR - PersosDocument25 pagesModernisasi Politik - Kel DPR - PersosCute PandaPas encore d'évaluation
- Lomba Menulis Milenial Merdeka 2022 PDFDocument3 pagesLomba Menulis Milenial Merdeka 2022 PDFawimPas encore d'évaluation
- Disintegrasi Bangsa Analisis PDFDocument5 pagesDisintegrasi Bangsa Analisis PDFputri rinda anggraeniPas encore d'évaluation
- DEMOKRASI PANCASILADocument12 pagesDEMOKRASI PANCASILAAnggita RahmadaniPas encore d'évaluation
- Pentingnya Pendidikan PolitikDocument5 pagesPentingnya Pendidikan PolitikFerdinanPas encore d'évaluation
- PMII Strategi PengembanganDocument12 pagesPMII Strategi PengembanganHamzah AliasPas encore d'évaluation
- KESEJAHTERAAN RAKYATDocument7 pagesKESEJAHTERAAN RAKYATIrfanPas encore d'évaluation
- Tugas 2 PKN - Dicky Julianto - 051653629Document7 pagesTugas 2 PKN - Dicky Julianto - 051653629dicky170051Pas encore d'évaluation
- Document 1Document2 pagesDocument 1cb bintangPas encore d'évaluation
- PPKN Tugas Mandiri 4.1 Dan 5.2Document2 pagesPPKN Tugas Mandiri 4.1 Dan 5.2Azfa Rihad FathanPas encore d'évaluation
- Cita-Cita Politik Islam PDFDocument164 pagesCita-Cita Politik Islam PDFDeni SupriadiPas encore d'évaluation
- SILA Kelima PANCASILADocument10 pagesSILA Kelima PANCASILAJemmi Andrian Matutina100% (41)
- Kliping Konsep Kelas Sosial Pada Teori PolitikDocument4 pagesKliping Konsep Kelas Sosial Pada Teori PolitikSiti AisyahPas encore d'évaluation
- Tugas KewarganegaraanDocument4 pagesTugas KewarganegaraanFaisal SyukrillahPas encore d'évaluation
- Politik identitas dan kebhinekaan IndonesiaDocument6 pagesPolitik identitas dan kebhinekaan IndonesiaVincent MarlinoPas encore d'évaluation
- Globalisasi Terhadap PolitikDocument6 pagesGlobalisasi Terhadap PolitikLisani ErizaPas encore d'évaluation
- Pertemuan 12Document9 pagesPertemuan 12dhifakafa10Pas encore d'évaluation
- Azu Kesuma Ilmu Politik UasDocument10 pagesAzu Kesuma Ilmu Politik UasSaskia OktaviaPas encore d'évaluation
- HAM Indonesia DinamikaDocument6 pagesHAM Indonesia DinamikaEnggal SantosoPas encore d'évaluation
- TM 2 Ips - Siti KhoiriyahDocument3 pagesTM 2 Ips - Siti KhoiriyahNiLa CahyoPas encore d'évaluation
- Sistem Politik Indonesia Era ReformasiDocument14 pagesSistem Politik Indonesia Era ReformasiKholikPas encore d'évaluation
- Kelas XIDocument23 pagesKelas XIFeRi100% (3)
- Aryani 043242622 T1 IPEM4437Document3 pagesAryani 043242622 T1 IPEM4437Ria AryaniPas encore d'évaluation
- Reformasi Merupakan Suatu Gerakan Yang Menghendaki Adanya Perubahan Kehidupan BermasyarakatDocument4 pagesReformasi Merupakan Suatu Gerakan Yang Menghendaki Adanya Perubahan Kehidupan BermasyarakatnindifkPas encore d'évaluation