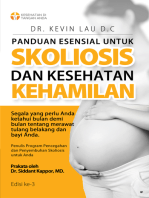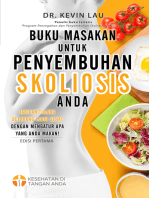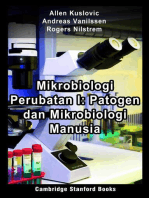Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
MKN Des2005 PDF
MKN Des2005 PDF
Transféré par
Abdurrachman MachfudzTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
MKN Des2005 PDF
MKN Des2005 PDF
Transféré par
Abdurrachman MachfudzDroits d'auteur :
Formats disponibles
Sindroma Ovarium Polikistik
Budi R. Hadibroto
Departemen Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
RSUP H. Adam Malik RSUD. Dr. Pirngadi Medan
Abstrak: Sindroma ovarium polikistik merupakan gangguan fungsional dari poros hipotalamushipofise ovarium berkaitan anovulasi. Dalam keadaan relatif terdapat keseimbangan antara
gonadotropin dan steroid seks. Pada keadaan ini, kadar LH relatif tinggi dan kadar FSH relatif
rendah, sehingga meningkatkan nisbah LH:FSH. Kadar oestradiol sama dengan fase folikuler awal.
Sebagai respon atas meningkatnya kadar LH, terjadi peningkatan kadar testosteron, androstendion
dan DHA yang disekresikan oleh ovarium. Pada jaringan perifer sebahagian dari hormon androgen
tersebut diubah menjadi oestron. Sebagai respon terhadap tingginya kadar hormon androgen, SHBG
berkurang sekitar 50%, mendorong meningkatnya proporsi hormon androgen yang aktif dan tidak
terikat. Lazim ditemukan efek samping akibat peningkatan hormon androgen. Demikian kompleksnya
sindroma ini sehingga melibatkan kompartemen yang lain. Kelenjar adrenal menghasilkan
peningkatan kadar DHAS. Umumnya dijumpai pula reistensi insulin.
Kata kunci: anovulasi, hiperandrogen, ovarium polikistik
Abstract: Polycystic ovarian syndrome is a functional derangement of the hypothalamo-pituitary
ovarian axis associated with anovulation. A relatively steady state of gonadothropins and sex
steroids exists. In this steady state , luteinizing hormone (LH) levels are relatively high and follicle
stimulating hormone (FSH) levels are relatively low, leading to an elevated LH:FSH ratio. Oestradiol
levels are similar to those in the early follicular phase. In response to the elevated levels of LH,
increased levels of testosterone, androstendione and DHA (dehydroepiandros-terone) are secreted by
the ovary. Some of these androgens are converted to oestrone in peripheral tissues. In response to
high androgen levels, sex hormone binding globulin (SHBG) is reduced by about 50%, leading to an
increase in the proportion of unbound, active, androgens. Hence, androgenic side effects are common,
despite only a modest rise in serum total testosterone levels.The syndrome is complex and other
compartments become involved. The adrenal gland produces eleveated levels of DHAS
(dehydroepiandrosterone sulphate). Insulin resistance (resistance to insulin-stimulated glucose
uptake) is also common.
Key words: anovulation, hyperandrogen, polycystic ovarian
PENDAHULUAN
Sindroma ovarium polikistik (SOPK)
merupakan masalah endokrinologi reproduktif
yang sering terjadi dan sampai saat ini masih
menjadi kontroversi.
Sindroma ovarium polikistik menyebabkan 5%-10% wanita usia reproduksi menjadi
infertil.1
Gambaran klinis dan biokimia beragam,
masih menjadi perdebatan apakah keadaan ini
merupakan penyakit tunggal atau merupakan
kumpulan gejala. Pada akhir-akhir ini semakin
jelas bahwa SOPK bukan hanya penyebab
tersering kejadian ovulasi dan hirsutisme namun
juga
berhubungan
dengan
gangguan
metabolisme yang memiliki pengaruh penting
dalam kesehatan wanita.1,2
Sejak dikemukan oleh Stein dan Leventhal
pada tahun 1935, pada mulanya diterangkan
bahwa SOPK merupakan suatu kumpulan gejala
yang terdiri dari amenorrhea, haid yang tidak
teratur, infertil, hirsutisme dan obesitas.
Belakangan diketahui bahwa wanita dengan
siklus haid yang reguler dengan keadaan
hiperandrogen dengan atau tanpa ovarium
polikistik juga dapat menderita SOPK. Selain itu
pada beberapa wanita dengan sindroma ini dapat
menderita ovarium polikistik tanpa tanda-tanda
klinis hiperandro-gen namun terdapat bukti
adanya disfungsi ovarium.3
Majalah Kedokteran Nusantara Volume 38 y No. 4 y Desember 2005
333
Tinjauan Pustaka
Menurut konsensus Rotterdam tahun 2003
mengenai SOPK, bahwa kriteria diagnostik
untuk SOPK adanya 2 dari 3 keadaan berikut
yaitu: oligomenorrhea atau anovulasi, tandatanda hiperandrogen secara klinis maupun
biokimia dan ovarium polikistik dimana
keadaan-keadaan
tersebut
diatas
bukan
disebabkan oleh hiperplasia adrenal kongenital,
tumor yang mensekresi androgen atau Cushing
Syndrome.4
Meskipun penyebab pasti penyakit ini
belum diketahui, namun terdapat kemajuan
dalam bidang endokrinologi, biokimia dan
farmakologi untuk memberikan pengobatan
yang menggembirakan, termasuk terapi yang
bersifat farmakologi maupun operatif. Tindakan
operatif memberikan angka keberhasilan yang
cukup tinggi.
hiperplastik yang mengalami luteinisasi sebagai
respon peningkatan kadar LH.1,3,5
GAMBARAN KLINIS
Kejadian SOPK dengan gejala klinis
beragam dan memberikan gambaran angka yang
bervariasi. Adam dkk, 1986 melaporkan bahwa
pada penderita ovarium polikistik (OPK) yang
didiagnosa secara sonografi, didapati 30%
menderita
amenorrhea,
75%
dengan
oligomenorrhea, dan 90% didapati adanya
peningkatan konsentrasi kadar luteinizing
hormon (LH) dan androgen.2,3
Tanda dan gejala klinis SOPK didapat dari
keluhan utama pasien maupun dari pemeriksaan
klinis.
Keadaan hiperandrogen memiliki tandatanda seperti hirsutisme, timbulnya jerawat
bahkan dapat timbul pola alopesia seperti lakilaki. Hirsutisme didefinisikan sebagai suatu
keadaan munculnya bulu-bulu
kasar pada
wanita seperti pola pertumbuhan pada laki-laki
seperti diatas bibir, dagu, dada, abdomen bagian
atas maupun dipunggung. Keadaan anovulasi
kronis ditandai adanya gangguan haid seperti
amenorrhea, oligomenorrhea, perdarahan uterus
disfungsional dan akan menimbulkan infertilitas.
Menariknya penelitian Conway dkk (1989)
menunjukkan 20% pasien SOPK tidak
mengalami gangguan haid.6
Selain
itu
akhir-akhir
ini
dalam
mengevaluasi
seorang
pasien
dengan
kemungkinan SOPK penting juga dijajaki
tentang kemungkinan adanya tanda-tanda
resistensi insulin. Obesitas merupakan kunci
adanya sindroma resistensi insulin. Dari
pemeriksaan klinis tanda adanya resistensi
insulin didapati adanya acanthosis nigricans.2,6
PATOGENESA
DIAGNOSIS
Patogenesa SOPK kurang jelas diketahui,
namun
diduga
bahwa
defek
primer
kemungkinan karena adanya resistensi insulin
yang
menyebabkan
hiperinsulinemia.1
Konsentrasi insulin dan LH didalam sirkulasi
secara umum akan meningkat. Sel theca yang
membungkus
folikel
dan
memproduksi
androgen yang nantinya akan dikonversi
menjadi estrogen didalam ovarium menjadi
sangat aktif dan responsif terhadap stimulasi
LH. Sel theca akan lebih besar dan akan
menghasilkan androgen lebih banyak. Sel-sel
theca yang hiperaktif ini akan terhalang
maturasinya sehingga akan menyebabkan sel-sel
granulosa
tidak
aktif
dan
aktifitas
aromatisasinya menjadi minimal. Akibat
ketidakmatangan folikel-folikel tersebut maka
terjadi pembentukan kista-kista dengan diameter
antara 26 mm dan masa aktif folikel akan
memanjang, sehingga akan terbentuk folikelfolikel baru sebelum folikel yang lain mati.
Folikel-folikel tersebut akan berbentuk seperti
kista yang dilapisi oleh sel-sel theca yang
Diagnosis SOPK berdasarkan kombinasi
kriteria klinis.,sonografi dan biokimia. Pada
wanita
yang
menderita
amenorrhea,
kemungkinan timbulnya SOPK bila didapati
satu atau lebih gambaran berikut :2,3,4,5,6
1. adanya
ovarium
polikistik
pada
pemeriksaan sonografi.
2. Hirsutisme
3. Hiperandrogenisme.
Pada wanita dengan siklus haid yang
normal adanya OPK pada pemeriksaan
sonografi menunjukkan adanya hirsutisme yang
disebabkan oleh karena faktor ovarium.
ANGKA KEJADIAN
334
Tabel 1.
Kriteria Diagnostik Sindroma Resistensi Insulin
Adanya 3 atau lebih keadaan berikut :
Lingkar pinggang > 88 cm
Kadar trigliserida 150 mg/dl
Kadar HDL kolesterol < 50 mg/dl
Tekanan Darah 130/85 mmHg
Kadar gula darah puasa 110 mg/dl
Dikutip dari 4
Majalah Kedokteran Nusantara Volume 38 y No. 4 y Desember 2005
Budi R. Hadibroto
PEMERIKSAAN PENUNJANG
Pemeriksaan Sonografi
Pemeriksaan sonografi pelvis akan sangat
mendukung untuk menegakkan diagnosa SOPK.
Jumlah folikel dan volume ovarium penting
dalam pemeriksaan sonografi. Adam dkk
menetapkan kriteria SOPK secara sonografi
adalah dengan adanya kista folikel 10 buah
dengan diameter 2 8 mm dengan stroma yang
tebal. Jonard dkk mengajukan kriteria SOPK
secara sonografi dengan adanya peningkatan
luas ovarium (> 5,5 cm2) atau dengan volume
ovarium > 11 ml dan /atau adanya folikel 12
buah dengan diameter 2 9 mm. Kriteria yang
diajukan oleh Jonard dkk ini memiliki
spesifisitas 99% dan sensitivitas 75% untuk
mendiagnosa SOPK secara sonografi.6
Pemeriksaan Hormonal
Pemeriksaan hormonal pada penderita
SOPK memperlihatkan beberapa kelainan
endokrin. Beberapa hormon yang perlu
diperiksa :
1. Nisbah
luteinizing
hormon/follicle
stimulating hormon :
Nisbah 2,0 menunjukkan adanya suatu
SOPK
2. Kadar 17-hydroxyprogesteron :
Kadar 200 ng/dl mengkonfirmasikan
diagnosis SOPK.
3. Testosteron :
Kadar testosteron 150 ng/dl banyak
didapati pada penderita SOPK.
4. Dehydorepiandrosterone-sulfate (DHEAS)
:
Kadar DHEAS akan normal atau sedikit
meningkat pada penderita SOPK.
5. Prolaktin :
Lima sampai 30% pasien SOPK dilaporkan
mengalami hiperprolakti-nemia ringan.
6. Kadar gula darah puasa/rasio insulin :
< 7,0 pada orang dewas menunjukkan
adanya resistensi insulin.
< 4,5 pada pasien SOPK yang obesitas,
euglikemia.
PENATALAKSANAAN
Setelah SOPK didiagnosa dan penyebab
hiperandrogen telah disingkirkan, maka dapat
dilakukan penatalaksanaan untuk SOPK. Tujuan
terapi SOPK adalah :
1. Menghilangkan
gejala
dan
tanda
hiperandrogenisme.
2. Mengembalikan siklus haid menjadi
normal.
Sindroma Ovarium Polikistik
3.
4.
Memperbaiki fertilitas.
Menghilangkan gangguan
yang terjadi.6,7
metabolisme
Pendekatan terapi SOPK dewasa
dilakukan dengan 3 macam cara7 :
I. Non farmakologi
II. Farmakologi
III. Operatif
ini
I.
Non Farmakologi
Tanda dan gejala hirsutisme akan
memakan waktu cukup lama untuk kembali
normal setelah pemberian terapi antiandrogen.
Untuk menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh
pada penderita SOPK, banyak wanita
melakukan tindakan untuk menghilangkan bulubulu secara elektrolisis atau laser untuk tujuan
kosmetik.
Penurunan berat badan akan memberikan
pengaruh terhadap kadar hormon dalam
sirkulasi.
Satu penelitian menerangkan pada 6 orang
penderita SOPK yang mengalami penurunan
berat badan rata-rata sebesar 16,2 kg akan
menyebabkan penurunan kadar testosteron, 4
orang diantaranya terjadi ovulasi.7
II.
Farmakologi2,6,7,8
a.
Kontrasepsi oral
Tujuan pemakaian obat ini adalah untuk
menurunkan produksi steroid ovarium dan
produksi androgen adrenal, meningkatkan sex
hormon-binding
globulin
(SHBG),
menormalkan
rasio
gonadotropin
dan
menurunkan konsentrasi total testosteron dan
androstenedione didalam sirkulasi.
Mengembalikan seleksi haid yang normal,
sehingga dapat mencegah terjadinya hiperplasia
endometrium dan kanker endometrium.
Medroxyprogesteron asetat dapat dijadikan
sebagai terapi untuk menghilangkan gejala
hirsutisme. Dosis 150 mg intramuskular setiap 6
minggu selama 3 bulan atau 20 40 mg perhari.
b.
Antiandrogen
Fungsi kerja antiandrogen adalah untuk
menurunkan produksi testosteron maupun untuk
mengurangi kerja dari testosteron.
Beberapa antiandrogen yang tersedia antara
lain :
Cyproteron acetat yang bersifat kompetitifinhibisi
terhadap
testosteron
dan
dyhidrotestosteron pada reseptor androgen.
Dosis 100 mg perhari pada hari 5 15
siklus haid.
Majalah Kedokteran Nusantara Volume 38 y No. 4 y Desember 2005
335
Tinjauan Pustaka
Flutamide bersifat menekan biosintesa
testosteron. Dosis yang digunakan 250 mg
3 kali pemberian perhari selama 3 bulan.
Finasteride yang merupakan inhibitor
spesifik enzym 5 reduktase digunakan
dengan dosis 5 mg/hari.
c.
GnRh analog
Pemberian GnRh agonis akan memperbaiki
denyut sekresi LH sehingga luteinisasi prematur
dari folikel dapat dicegah dan dapat
memperbaiki rasio FSH/LH.
d.
Metformin
Bertujuan untuk menekan aktifitas
cytochrom P450c-17 ovarium, yang akan
menurunkan kadar androgen, LH dan
hiperinsulinemia. Diberikan dengan dosis 500
mg 3 kali pemberian perhari selama 30 hari.
e.
Clomiphene Citrat
Merupakan terapi pilihan untuk induksi
ovulasi dan mengembalikan fungsi fertilisasi.
Pada keadaan hiperandrogen pada wanita yang
anovulasi,
clomiphen
citrat
dilaporkan
meningkatkan frekwensi siklus ovulasi sampai
80% dengan rata-rata terjadi kehamilan sekitar
67%. Dosis diberikan 50 mg satu kali pemberian
perhari dengan dosis maksimal perhari dapat
ditingkatkan menjadi 200 mg.
III. Operatif
a.
Reseksi baji ovarium (Ovarian Wedge
Resection)
Reseksi baji ovarium dapat dilakukan
secara laparatomi atau laparoskopi. Reseksi baji
ovarium direkomendasi oleh Kistner dan Patton
terhadap pasien SOPK yang mengalami ovulasi
pada pemberian clomiphene citrat namun tidak
terjadi kehmailan. Keduanya menganjurkan
tindakan reseksi baji dilakukan pada pasien yang
tidak mengalami kehamilan setelah 7 atau 8 kali
siklus pengobatan dengan clomiphene citrat.
Pada reseksi baji ovarium dilakukan insisi 2 3
cm pada korteks ovarium yang menebal. Insisi
dibuat sesuai dengan alur ovarium, dan dihindari
daerah hilus ovarium untuk menghindari
terjadinya perdarahan yang banyak. Melalui
lubang insisi bagian medulla diangkat dan
sebanyak
mungkin
korteks
ovarium
dipertahankan.9
Gjonnaess (1984) melakukan prosedur
reseksi baji ovarium secara laparoskopi. Dengan
memakai elektrode unipolar dibuat 8 15
lubang sedalam 2 4 mm pada kapsul pada
masing-masing ovarium. Dengan tindakan ini
336
ovulasi dapat disembuhkan pada 92% pasien
dengan angka keberhasilan kehamilan sebesar
80%.10
b.
Pemgeboran ovarium dengan Laser secara
Laparoskopi (Laparoscopy Laser Ovarian
Drilling)
Tindakan pengeboran ovarium dengan
laser diperkenalkan dan digunakan untuk terapi
SOPK sejak 15 tahun terakhir. Dasar tindakan
ini adalah bahwa laser memiliki densitas power
yang terkontrol sehingga didapat kedalaman
penetrasi pada jaringan sesuai yang diharapkan
serta kerusakan jaringan akibat pengaruh panas
yang dapat diprediksi. Pemakaian laser juga
akan mengurangi resiko perlengketan.11
Beberapa jenis laser yang sering digunakan
adalah : karbon dioksida (CO2), argon dan
YAG.10,11,12 Tindakan pengeboran ovarium
dengan laser dilakukan dengan laparoskop
dengan diameter 10 mm yang dihubungkan
dengan laser CO2. Dapat digunakan CO2
ultrapulsa (40 80 W, 25 200 mJ) atau CO2
superpulsa (25 40 W). Seluruh folikel
subkapsular yang tampak divaporisasi dan
dibuat lubang ukuran 2 4 mm secara acak pada
stroma ovarium.9 Tahun 1997 tehnik tindakan
pengeboran ovarium dengan laser distandarisasi
dengan menggunakan jarum elektrode unipolar
yang ditusukkan kedalam kavum abdomen
secara tegak lurus, dibuat 10 15 tusukan pada
masing-masing ovarium dengan arus koagulasi
sebesar 40-W selama 2 detik pada masingmasing tusukan.11
Dengan menggunakan laser YAG, Huber
dkk (1988) melakukan pengeboran ovarium
sebanyak 3 5 buah pada masing ovarium
dengan panjang 5 10 mm dan kedalaman 4
mm. Tindakan ini berhasil memberikan ovulasi
spontan pada 5 dari 8 orang pasien yang
diterapi.
Danielle (1989) melakukan pengeboran
ovarium dengan menggunakan laser argon, CO2
atau kalium titanyl phosphate (KTP) dimana
dibuat tehnik 2 tusukan (two-puncture
technique) untuk drainage folikel subkapsular
yang tampak dan membuat lubang pada stroma
ovarium. Tindakan ini memberikan ovulasi
spontan pada 71% kasus.11,13
Dari beberapa penelitian penggunaan laser
untuk pengeboran ovarium didapati hasil ovulasi
spontan antara 70 80% dengan tingkat
keberhasilan kehamilan antara 56 80%.
Majalah Kedokteran Nusantara Volume 38 y No. 4 y Desember 2005
Budi R. Hadibroto
Sindroma Ovarium Polikistik
clomiphene citrate in polycystic ovary
syndrome. Kobe J Med Sci 2003;49(3):59
73.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Norman RJ, Wu R, Stankiewicz MT.
Polycystic ovary syndrome. Med J Aust
2004;180:132 37.
2.
Frank S. Polycystic ovary syndrome. N
Engl J Med 1995;333:853 61.
3.
Hershlag A, Peterson CM. Polycystic
ovarian
syndrome.
In:
Novaks
Gynecology, Berek JS editor. William &
Wilkins, New York, 1996.p 837 45.
4.
The Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored
PCOS Consensus Workshop Group.
Revised 2003 Consensus on diagnostic
criteria and long-term health risks Related
to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril
2004;81(1):19 25.
5.
Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical
Gynecologic Endocrinology and Infertility.
Sixth Edition. Lippincott Williams &
Wilkins, Philadelphia, 1999. p 487 573.
6.
Sheehan
MT.
Polycystic
ovarian
syndrome: diagnostic and management.
Clin Med Res 2004;2(1):13 27.
7.
Patel SR, Korytkowski MT. Treating
polycystic ovary syndrome: todays
approach. Women Health Primary Care
2000;3(2):109 113.
8.
Amin M, Abdel-Kareem O, Takekida S,
Moriyama T, Abd el Aal G, Maruo T.
Update management of non responder to
9.
Sanfilippo JS, Rock JA. Surgery for benign
disease of the ovary. In: Te Lindes
Operative
Gynecology,
Rock
JA,
Thompson JD editors. Lippincott-Raven
Publishers, Philadelphia, 1997. p 625 44.
10. Cohen J. Laparoscopic procedures for
treatment of infertility related to polycystic
ovarian syndrome. Hum Reprod Update
1996;2(4):337 44.
11. Pirwany I, Tulandi T. Laparoscopic
treatment of polycystic ovaries: is it time to
relinquish the procedure?. Fertil Steril
2003;80(2):241 51.
12. Palomba S, Orio F, Nardo LG, Falbo A,
Russo
T,
Corea
D.
Metformin
administration versus laparoscopic ovarian
diathermy in clomiphene citrate-resistant
women with polycystic ovary syndrome; A
prospective parallel randomized doubleblind placebo-controlled trial. J Clin Endo
Metab 2004;89(10):4801 09.
13. Amer SAK, Li TC, Ledger WL. Ovulation
induction using laparoscopic ovarian
drilling in women with polycystic ovarian
syndrome; predictors of success. Hum
Reprod 2004;19(8):1719 24.
Majalah Kedokteran Nusantara Volume 38 y No. 4 y Desember 2005
337
Vous aimerez peut-être aussi
- Teknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)D'EverandTeknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!D'EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Évaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (7)
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatD'EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanD'EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (4)
- Buku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!D'EverandBuku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (4)
- Program Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaD'EverandProgram Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (9)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaD'EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaÉvaluation : 2.5 sur 5 étoiles2.5/5 (2)